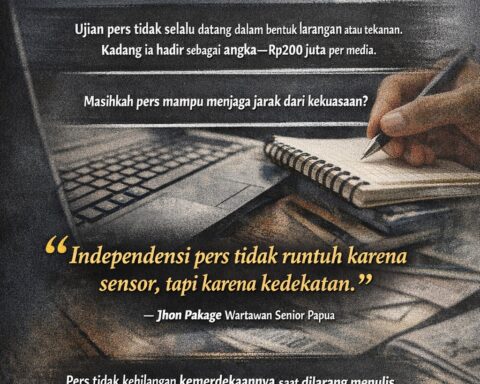Terima Kasih Tuan Rutte Untuk Tidak Menyebut Indonesia Dalam Pidato Pada Hari Senin, Tanggal 19 Desember 2022
MALUKU – Meskipun telah lewat hari selasa, tanggal 14 pebruari 2023, tetapi penulis ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke – 56 (hari selasa, tanggal 14 pebruari 1967) kepada yang terhormat Tuan Mark Rutte. Dalam usia yang relative masih muda, Tuan Rutte telah berhasil meraih prestasi terbaik di bidang politik sebagai Perdana Menteri terlama dalam sejarah Negara Kerajaan Belanda (sejak bulan Oktober tahun 2010).
Tuan Rutte adalah salah satu contoh hidup dari apa yang disebut oleh Charles Robert Darwin (1809-1882) dalam teori evolusinya, sebagai: “kelangsungan hidup dari yang terkuat (Survival of the fittest)”. Seandainya masih hidup, Niccolo Machiavelli (1469-1527) pasti akan sangat bangga dengan kekuasaan yang telah diraih oleh Tuan Rutte pada saat ini, sekalipun Tuan Rutte “mungkin” bukanlah seorang Machiavellis.
Jika penulis memberikan penilaian pribadi atas prestasi Tuan Rutte sebagaimana tersebut di atas – baik positive maupun negative – maka semua orang akan berpendapat sama terhadap penulis, yaitu, bahwa: “penilaian pribadi penulis itu adalah subjektive”. Oleh karena itu, atas/nama objektivitas, maka penulis mengutip penilaian paling akhir terhadap karakter politik Tuan Rutte sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh ketua komisi ‘Organisassi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa’ (the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)) Belanda, Kathleen Ferrier, ketika menanggapi pidato Tuan Rutte yang diucapkan pada hari senin, tanggal 19 desember 2022 itu: “saya melihat seorang perdana menteri yang rendah hati, yang memperhatikan fakta-fakta, dan berkata bahwa dia telah belajar dan menantikan masa depan”.
Disamping itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Tuan Rutte yang tidak menyinggung Indonesia sedikitpun bahkan tidak menyebut nama Indonesia samasekali dalam pidato pada hari senin, tanggal 19 desember 2022. Sebab, Jika Tuan Rutte meminta maaf kepada Indonesia, maka apa bedanya Tuan Rutte dengan ‘Pontius Pilatus’ (Gubernur (Prefek) ke-5 dari Provinsi Yudea dalam Kekaisaran Romawi (26M-36M)) yang sambil “mencuci tangan” menyerahkan ‘Yesus dari Nazareth’ (Yesus Kristus) kepada Para Imam Kepala dan para Tetua Orang Yahudi seraya berkata: “Aku tidak bersalah atas darah orang ini; itu urusan kamu sendiri! (I am innocent of this man’s blood; it is your responsibility!)” (?) (Matius, 27: (24) (Matthew, 27: (24)).
Di Indonesia sendiri, pidato Tuan Rutte telah memunculkan polemik dan kontroversi. Pidato Tuan Rutte yang hanya berdurasi 20 (dua puluh) menit itu, telah ditafsirkan oleh para wartawan, politisi, sejarawan, dan akademisi di Indonesia, seperti “orang awam” menafsirkan kitab suci yang sudah berusia ribuan tahun. Tetapi, Tuan rutte tidak harus merasa bersalah dengan tidak menyampaikan pernyataan permintaan maaf atas perbudakan di masa lalu kepada Indonesia. Penulis sangat yakin, Tuan Rutte yang pragmatis dalam urusan ini, tidak akan pernah merasa bersalah apalagi merasa menyesal.
Sebab, Indonesia baru ada pada tahun 1956 berdasakan Undang-Undang nomor: 13 yang diterbitkan pada hari kamis, tanggal 3 Mei 1956 tentang Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan ‘Perjanjian Konperensi Meja Bundar (KMB)’ (the Round Table Conference / de Ronde Tafel Conferentie (RTC)). Dimana melalui Undang-Undang ini, Indonesia “mengkhianati” ‘Majelis Permusyawaratan Federal’ (Bijeenkomst voor Federaale Overleg (BFO)) dan Negara Kerajaan Belanda dengan membatalkan secara ‘sepihak’ (unilateral) hasil keputusan KMB/RTC.
(Hasil keputusan KMB/RTC itu sendiri ditandatangani pada hari selasa, tanggal 27 desember 1949, di Paleis op de Dam, Amsterdam, Belanda, oleh Ratu Juliana Louise Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau (1909-2004) yang mewakili Mahkota Negara Kerajaan Belanda; Drs. Mohammad Hatta (1902-1980) mewakili Negara ‘Republik Indonesia’ (RI) yang dibentuk pada hari jumat, tanggal 17 agustus 1945; dan Mayor Jenderal (KNIL) Syarif Abdul Hamid Alkadrie (1913-1978) bergelar Sultan Hammid II dari Pontianak, Kalimantan Barat, mewakili BFO yang dibentuk pada hari rabu, tanggal 7 juli 1948).
Sementara itu, hasil keputusan KMB/RTC yang salah satunya adalah membentuk Negara ‘Republik Indonesia Serikat’ (RIS) pada hari selasa, tanggal 27 desember 1949, telah terdaftar di Sekretariat ‘Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)’ (the United Nations (UN)) dibawah nomor: 894, pada hari senin, tanggal 14 Agustus 1950, 3 (tiga) hari sebelum ‘orang-orang Yogyakarta’ (Mr. Supomo, Mr. Sartono, dan Ir. Sukarno) dengan secara ‘sepihak’ (unilateral) membentuk ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia’ (NKRI) pada hari kamis, tanggal 17 agustus 1950.
Terhadap pembentukkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 17 agustus 1950 (the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), 17 august 1950)” secara ‘sepihak’ (unilateral) oleh “orang-orang Yogyakarta (Supomo, Sartono, dan Sukarno)”, H. J. Kruls, LL.D., menyatakan, bahwa: “Negara Republik Indonesia (RI), 17 agustus 1945’ (the State of the Republic of Indonesia (RI), 17 august 1945) dalam ‘Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), 27 desember 1949’ (the United States of the Republic of Indonesia (RIS), 27 december 1949) telah membentuk suatu ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 17 agustus 1950’ (the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), 17 august 1950) yang “sepenuhnya ‘tidak sesuai hukum’ (ilegal)” dan melanggar prinsip ‘Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri’ (the Right of Self-Determination) dari rakyat dalam wilayah (bekas) Hindia-Belanda, termasuk juga telah melanggar ‘Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri’ (the Right of Self-Determination) dari rakyat dalam wilayah Maluku Selatan”[1]. Itupun, Indonesia baru ada sebagai suatu negara, dan tidak ada sebagai suatu bangsa. Sebagai bangsa, Indonesia masih dalam proses, dan proses itu belum selesai. Bahkan mungkin: “tidak akan pernah selesai!!!”[2].
Setelah membentuk “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 17 agustus 1950 (the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), 17 august 1950)” dengan secara ‘sepihak’ (unilateral), “orang-orang Yogyakarta (Supomo, Sartono, dan Sukarno)” juga dengan secara ‘sepihak’ (unilateral) membubarkan 16 (enam belas) negara bagian dalam “Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), 27 desember 1949 (the United States of the Republic of Indonesia (RIS), 27 december 1949)” tanpa membubarkan “Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), 27 desember 1949 (the United States of the Republic of Indonesia (RIS), 27 december 1949)” itu sendiri[3]. Dalam peristiwa ini, Indonesia telah “menipu” seluruh dunia, tetapi seluruh dunia – termasuk Belanda – bersikap acuh ta’ acuh seperti patung 3 (tiga) monyet yang masing-masing monyet menutup mata, telinga, dan mulut.
Mengenai “Negara Republik Indonesia (RI), 17 agustus 1945 (the State of the Republic of Indonesia (RI), 17 august 1945)”, Belanda tidak perlu memberikan pengakuan. Sebab, jika Belanda mengakui “Negara Republik Indonesia (RI), 17 agustus 1945 (the State of the Republic of Indonesia (RI), 17 august 1945)”, maka Belanda telah bertindak seperti kata orang bijak: “Mencoreng wajah sendiri” dan/atau “Menggosok tinja di wajah sendiri”. Suatu bentuk tindakan “membuat malu diri sendiri”, yaitu: “mempermalukan ‘Mahkota Negara Kerajaan Belanda’ (Ratu Juliana Louise Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau (1909-2004))”, yang telah menandatangani sendiri ‘dokumen piagam penyerahan kedaulatan’ (document of the charter of transfer of sovereignty) di Paleis op de Dam, Amsterdam, Belanda, pada hari selasa, tanggal 27 desember 1949.
Berdasarkan “dokumen piagam penyerahan kedaulatan (document of the charter of transfer of sovereignty)” sebagaimana tersebut di atas, Negara Kerajaan Belanda tidak menyerahkan kedaulatan kepada “Negara Republik Indonesia (RI), 17 agustus 1945 (the State of the Republic of Indonesia (RI), 17 august 1945)” apalagi kepada “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 17 agustus 1950 (the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), 17 august 1950)”, tetapi Negara Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada “Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), 27 desember 1949 (the United States of the Republic of Indonesia (RIS), 27 december 1949)”: “Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada ‘Republik Indonesia Serikat’ (RIS – penulis) dengan tidak ada syarat lagi dan dengan tidak dapat dicabut kembali, dan karena itu mengakui ‘Republik Indonesia Serikat’ (RIS – penulis) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat (The Kingdom of the Netherlands transfers sovereignty over Indonesia completely to “the Republic of the United States of Indonesia” unconditionally and irrevocably, and therefore recognizes “the Republic of the United States of Indonesia” as an independent and sovereign state)”.
Seharusnya, ‘Tuan Rutte’ (Pemerintah Negara Kerajaan Belanda) meminta maaf kepada ‘kami’ (Bangsa Alifuru yang ada di kepulauan Maluku (selatan)). Sebab dalam wilayah ‘India-Timur’ (Oost-Indie), kamilah yang “diperbudak” oleh bangsa Belanda untuk pertamakalinya. Erik van Zwam, dalam tulisan dibawah judul, Waarom Nederland Geen Excuses Aanbiedt voor de Grootscheepse Slavernij in Indonesie, di laman majalah Trouw, menyatakan bahwa, Belanda memulai “perbudakan” di ‘India-Timur’ (Oost-Indie) ketika ‘Persatuan Perusahaan India Timur (Belanda)’ (Vireenigde Oost-indische Compagnie (VOC)) datang ke kepulauan Banda di kepulauan Maluku pada tahun 1621.
“Permintaan maaf, kompensasi, dan pengakuan” bukannya tidak penting bagi kami, tetapi kami tidak akan berperilaku “cengeng” seperti orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai bangsa Indonesia, yang selalu merengek-rengek menuntut “permintaan maaf, kompensasi, dan pengakuan” dari Belanda, sementara tuntutan Indonesia itu sendiri tidak memiliki ‘alas hak’ (title) yang sah. Bagi kami, “permintaan maaf” tidak akan dapat menghidupkan kembali nenek moyang kami yang telah mati karena perbudakan di masa lalu; “kompensasi” tidak akan dapat membayar lunas kerugian yang telah kami tanggung selama 335 (tiga ratus tiga puluh lima) tahun (1621-1956); dan “pengakuan” hanyalah suatu bentuk tindakan politik yang – sekalipun memiliki akibat hukum – dapat berubah kapan saja (mengikuti arah perubahan kepentingan (politik)).
Perbuatan Belanda terhadap kami yang lebih kejam daripada perbudakan di masa lalu adalah, “kolaborasi” antara Belanda dengan ‘Indonesia’ (Jawa) yang memindahkan dari ‘Indonesia’ (Jawa) ke Belanda: “5.000 (lima ribu) orang ‘Tentara Kerajaan Hindia Belanda’ (Koninklijk Nederlands(ch)-Indisch Leger (KNIL)) keturunan Maluku (12.500 (dua belas ribu lima ratus) orang beserta keluarga)”. Mereka bersedia untuk dipindahkan dari ‘Indonesia’ (Jawa) ke Belanda adalah akibat dari sebab Belanda telah berjanji untuk mengembalikan mereka ke Maluku (selatan) setelah lewatnya jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal mereka tiba untuk pertama kalinya di Belanda. Suatu janji yang tidak pernah ditepati oleh Belanda sampai/dengan saat ini.
(Kolaborasi sebagaimana tersebut di atas, mengingatkan kita pada kolaborasi antara Negara ‘Kerajaan Ketiga’ (Drittes Reich) dan/atau Negara ‘Jerman Nazi’ (NS-Staat) pimpinan Fuehrer Adolf Hitler (1889-1945) dengan Negara ‘Perancis Vichy’ (Regime de Vichy) pimpinan Marsekal Henri Philippe Benoni Omer Joseph Petain (1856-1951) yang mengirimkan ribuan Bangsa Yahudi ke kamp-kamp konsentrasi sebagai tawanan (1939-1945); dan juga mengingatkan kita pada kolaborasi antara Kekaisaran Jepang dengan ‘Koesno Sosrodihardjo (1901-1970) alias Soekarno’ (Presiden pertama ‘Negara Republik Indonesia (RI), 17 agustus 1945’ (the State of the Republic of Indonesia (RI), 17 august 1945)) yang mengirimkan ribuan orang ‘India-Timur’ (Oost-Indie) ke kamp-kamp kerja paksa sebagai ROMUSHA (1942-1945). Akan tetapi, berbeda dari “Marsekal Petain” yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan yang dibentuk Sekutu, “Presiden Sukarno” justeru dibiarkan bebas melenggang begitu saja tanpa diadili oleh ‘sekutu’ (termasuk oleh Belanda)) [4].
Perbuatan Belanda sebagaimana tersebut di atas, dapat dikategorikan sebagai “memindahkan penduduk secara paksa” yang merupakan suatu bentuk “pelanggaran berat ‘Hak Asasi Manusia (HAM)”, yaitu: “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan”. Tetapi “pemindahan paksa” ini, dilakukan oleh Belanda secara terselubung melalui “tipuan secara halus” untuk menghindari terpenuhinya unsur-unsur pidana pelanggaran berat HAM tentang “kejahatan terhadap kemanusiaan” sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam ‘Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional’ (Rome Statute of the ‘International Criminal Court’ (ICC)).
Layaknya seorang pemain sulap di panggung pasar malam, “tipuan” Belanda tidak hanya sekali. Sebab, janji Belanda untuk meleburkan ke – 5.000 (lima ribu) KNIL sebagaimana tersebut di atas kedalam kesatuan ‘Tentara Kerajaan Belanda’ (Koninklijk Leger (KL)) juga tidak kunjung ditepati hingga 99% dari mereka telah tiada. Bahkan sebelum ke – 5.000 (lima ribu) KNIL tersebut menginjakkan kaki mereka di tanah Belanda, Belanda telah melucuti status kemiliteran mereka, sehingga mereka pada akhirnya dengan secara terpaksa harus menjejakkan kaki mereka di tanah Belanda sebagai suatu bangsa tanpa status kenegaraan yang jelas. Sekarang – 73 (tujuh puluh tiga) tahun sudah (1950-2023) – Belanda “membiarkan” ‘keturunan mereka’ (80.000 (delapan puluh ribu) orang) menjadi ‘Belanda Hitam’ (Zwart Nederlands) demi dan untuk mempertahankan ikatan persahabatan antara ‘Belanda Putih’ (Wit Nederlands) dengan Indonesia. Suatu bentuk “pembiaran” yang merupakan “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Suatu bentuk “pelanggaran berat HAM”.
Seandainya Belanda “tidak ‘ingkar janji’ (wan prestasi)”, maka tidak akan pernah terjadi:
- Peristiwa pembakaran gedung kedutaan besar “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 17 agustus 1950 (the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), 17 august 1950)” di kota den Haag (the Haque) pada tahun 1966;
- Peristiwa penyerangan rumah dinas duta besar “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 17 agustus 1950 (the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), 17 august 1950)” di kota Wassenaar pada hari senin, tanggal 31 agustus 1970 (Dalam peristiwa ini, seorang polisi berkebangsaan Belanda tewas tertembak);
- Peristiwa rencana penculikan Ratu Juliana Louise Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau (1909-2004) pada bulan desember tahun 1975, yang di-ikuti dengan peristiwa pembajakan kereta api di kota Wijster, dan yang dibarengi pula dengan peristiwa penyerangan gedung konsulat “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 17 agustus 1950 (the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), 17 august 1950)” di kota Amsterdam pada bulan dan tahun yang sama (Dalam peristiwa ini, 3 (tiga) orang berkebangsaan Belanda tewas dieksekusi, dan seorang berkebangsaan Indonesia terluka parah);
- Peristiwa pembajakan kereta api di kota de Punt yang dibarengi dengan penyanderaan di kota Bovensmilde pada tahun 1977 (Dalam peristiwa ini, 6 (enam) orang berkebangsaan ‘Alifuru’ (Maluku), dan 2 (dua) orang berkebangsaan Belanda tewas tertembak); dan
- Peristiwa pendudukan balai provinsi di kota Assen pada tahun 1978.

Demi menjaga hubungan baik antara Belanda dengan Indonesia, pemerintah Belanda “tega” untuk mengorbankan Bangsa ‘Alifuru’ (Maluku) yang telah menunjukkan ‘kesetian sepanjang masa’ (door de eeuwen trouw) terhadap Mahkota Negara Kerajaan Belanda, bahkan pemerintah Belanda “rela” untuk mengorbankan Bangsa Belanda sendiri. Tindakan Belanda yang “tidak menepati janji” adalah “sebab utama yang tidak disebabkan lagi (causa prima)” dari semua peristiwa yang pernah terjadi sebagaimana tersebut di atas. Jadi, adalah ‘salah’ (tidak benar), tidak pada tempatnya, tidak berdasar, tidak patut, tidak pantas, tidak layak dan tidak wajar, bahkan tidak bertanggungjawab samasekali, jika Belanda mempersalahkan “Bangsa ‘Alifuru’ (Maluku) di Belanda” atas terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut di atas.
Kami mengakui bahwa, Kesalahan fatal yang selalu kami lakukan berulangkali dari dahulu hingga sekarang sebagai suatu bentuk kebebalan kami adalah, bahwa: “Kami Melupakan”. Kecenderungan kami untuk “cepat melupakan segala sesuatu” telah merupakan sebab yang membawa akibat bangsa-bangsa lain di ‘India-Timur’ (Oost-Indie) menilai kesetiaan kami kepada Belanda sama seperti kesetiaan seekor anjing kepada tuannya, sehingga kami disebut oleh bangsa-bangsa lain di ‘India-Timur’ (Oost-Indie), sebagai: “Anjing Belanda (Nederlandse Hond)”. Suatu istilah yang lebih merupakan suatu bentuk penghinaan daripada suatu bentuk pujian[5]. Meskipun sebagian dari kami masih nyaman untuk tetap dan terus menjadi “anjing Belanda (Nederlandse hond)” bahkan menjadi “anjing Indonesia (Indonesische hond)” yang nasibnya ditentuan oleh Tuan-tuan Belanda dan/atau oleh Tuan-tuan Indonesia, tetapi sebagian dari kami telah belajar untuk kembali menjadi “manusia seutuhnya” yang dapat menentukan nasib kami sendiri.
73 (tujuh puluh tiga) tahun silam – tepatnya pada hari selasa, tanggal 25 April 1950 – kami telah menentukan nasib kami sendiri sebagai suatu bangsa yang berdaulat melalui pernyataan kemerdekaan “Republik Maluku Selatan (RMS) (the Republic of South Moluccas)” sebagai suatu Negara. Perihal ini adalah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Gesina Hermina Johanna van der Molen, bahwa: “Republik Maluku Selatan (RMS), 25 april 1950 (the Republic of South Moluccas (RMS), 25 april 1950) sebagai suatu negara memiliki hak yang sempurna untuk memberlakukan ‘hak untuk menentukan nasib sendiri’ (the Right of Self-Determination) mereka … Sangat sedikit negara dapat merdeka secara ‘sah menurut hukum’ (legal), sama seperti “Negara Republik Maluku Selatan (RMS), 25 april 1950 (the Republic of South Moluccas (RMS), 25 april 1950) ini”[6]. Bahkan Hendrik Jan Roethof, menyatakan, bahwa: “Negara Republik Maluku Selatan (RMS), 25 april 1950 (the Republic of South Moluccas (RMS), 25 april 1950) memiliki status hukum yang sangat besar melebihi negara-negara lain yang kedaulatannya telah diakui dan telah diterima sebagai anggota PBB/UN”[7].
Akan Tetapi, seluruh dunia – termasuk Belanda – menikam kami seperti Brutus menikam Julius Cesar, sehingga kami harus berjuang sendirian dalam menghadapai invasi yang disusul kemudian dengan agresi dan pada akhirnya aneksasi, yang dilakukan oleh Indonesia atas Negara kami: “Republik Maluku Selatan (RMS), 25 april 1950 (the Republic of South Moluccas (RMS), 25 april 1950)” [8].
Dalam hubungan dengan aneksasi yang dilakukan oleh “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 17 agustus 1950 (the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), 17 august 1950)” terhadap “Negara Republik Maluku Selatan (RMS), 25 april 1950 (the Republic of South Moluccas (RMS), 25 april 1950)”, Noelle Higgins, menyatakan, bahwa: “Aneksasi yang tidak sah oleh “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 17 agustus 1950 (the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), 17 august 1950)” terhadap “Negara Republik Maluku Selatan (RMS), 25 april 1950 (the Republic of South Moluccas (RMS), 25 april 1950)” tidak menghormati hak rakyar Maluku Selatan atas ‘hak untuk menentukan nasib sendiri’ (the Right of Self-Determination) dari Rakyat Maluku Selatan, dan juga tidak menghormati keberadaan “Negara Republik Maluku Selatan (RMS), 25 april 1950 (the Republic of South Moluccas (RMS), 25 april 1950)” sehingga menimbulkan perkara hukum”[9].
Namun demikian, sekalipun invasi, agresi maupun aneksasi telah bertentangan dengan:
(1) Pasal 1, Pakta Paris dan/atau Pakta Briand-Kellogg (General Treaty for the Renunciation of War) tahun 1928;
(2) The Stimpson Doctrine of Non-Recognition, tahun 1932;
(3) Piagam PBB tahun 1945, Pasal 2: ayat (4) dari Bab I tentang Tujuan-tujuan dan Prinsip-prinsip (Charter of the United Nations 1945, article 2: (4), Chapter I: Purposes and Principles);
(4) Pasal 17, Piagam Bogota – ‘Piagam Organisasi Negara-negara Amerika’ (Organization of American States (OAS) Charter) tanggal 30 April 1948;
(5) Pasal 11, Rancangan Deklarasi tentang ‘Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Dasar Negara-Negara’ (Fundamental Rights and Duties of States), tahun 1949;
(6) Paragraph 10, ‘deklarasi prinsip-prinsip dasar hukum internasional tentang hubungan baik dan kerja-sama antar negara’ (Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations), tahun 1970;
(7) Putusan pengadilan perang Nurnberg; dan
(8) ‘Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional’ (Rome Statute of the ‘International Criminal Court’ (ICC))”, tetapi seluruh dunia – termasuk Belanda – diam seribu bahasa.
Seperti Belanda di masa lalu, Indonesia juga “merampok kekayaan” kami pada saat ini, dan membiarkan kami menjadi salah satu bangsa “paling miskin” dan “paling bodoh” di ‘India-Timur’ (Oost-Indie). Dalam hubungan dengan perihal ini, benarlah kata-kata Dr. Teungku Hasan Muhammad di Tiro, MS., MA., LLD., Phd. (1925-2010), bahwa: “Indonesia (adalah) sekedar kelanjutan Hindia-Belanda seutuhnya secara politis, ekonomi dan yuridis”[10]. Dan, jika kami mengenang kembali kata-kata DR. Willem Karel Tehupeiory (1883-1946), bahwa: “Kekuasaan Belanda adalah lebih baik dari kekuasaan feodal Jawa”[11], maka kami masih akan menanggung kemiskinan dan kebodohan dalam jangka waktu panjang dibawah kekuasaan Neofasis-Neofeodal-Neokolonial Indonesia.
Tulisan ini, bukan merupakan suatu bentuk pengaduan kami kepada Belanda. Sebab dengan menimbang budaya politik Belanda yang masih bersifat “pragmatis”, maka sekalipun tulisan ini adalah suatu bentuk pengaduan kami kepada Belanda, Belanda hanya akan peduli sepanjang pengaduan kami memberikan manfaat dan/atau keuntungan untuk Belanda – baik manfaat/keuntungan politik maupun manfaat/keuntungan ekonomi. Kami sangat yakin, Belanda lebih peduli kepada kolaboratornya dan/atau konspiratornya, yaitu: “Indonesia”.
Melalui tulisan ini, kami ingin mengingatkan bangsa Belanda bahwa, semua peristiwa yang terjadi dalam wilayah – dan dalam hubungan dengan – ‘India-Timur’ (Oost-Indie) sejak tahun 1602 hingga saat ini, bahkan nanti di masa depan, tidak akan pernah terjadi jika pemerintah Belanda tidak membuat “garis-garis artifisial” yang menjadikan wilayah ‘India-Timur’ (Oost-Indie), sebagai: “wilayah artifisial”.
“wilayah artifisial” sebagaimana tersebut di atas, pada hari Jumat, tanggal 17 agustus 1945, diklaim secara ‘sepihak’ (unilateral) tanpa ‘alas hak’ (title) yang sah oleh orang-orang yang menamakan diri mereka, sebagai: “bangsa Indonesia”. “Garis-garis Artifisial” itu telah mengorbankan “300 bangsa antropologis” yang ada dalam wilayah ‘India-Timur’ (Oost-Indie) dibawah kekuasaan mereka-mereka yang menamakan dirinya, sebagai: “bangsa Indonesia”.
Salah satu bangsa antropologis yang menjadi korban dari “garis-garis artifisial” itu, adalah: “Bangsa Alifuru di Kepulauan Maluku”. Bagi kami, ini telah menjadi: “memoria passionis”[12].
Penulis telah memulai pengerjaan tulisan ini sejak awal bulan pertama tahun 2023, tetapi tulisan ini sengaja baru dipublikasikan sekarang oleh penulis pada hari ini, hari senin, tanggal 15 Mei 2023, sebagai suatu bentuk penghargaan dan penghormatan penulis atas “perang” yang dikobarkan oleh bangsa Alifuru di Kepulauan Maluku – bukan oleh bangsa Indonesia, sebagaimana dinyatakan oleh orang-orang yang menamakan diri mereka, sebagai: “bangsa Indonesia” – terhadap bangsa Belanda pada tahun 1817. Sebab pada tahun 1817, tidak ada apapun yang bernama Indonesia. Bahkan sebagai suatu katapun, Indonesia tidak ada. Kata Indonesia itu sendiri baru diciptakan untuk pertamakalinya oleh George Samuel Windsor Earl (1813-1865), seorang navigator berkebangsaa Inggris pada tahun 1850[13]. 33 (tiga puluh tiga) tahun (1817-1850) setelah berakhirnya peperangan antara bangsa Belanda melawan bangsa Alifuru di Kepulauan Maluku.
“Perlawanan” sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Thomas Matulessy (8 juni 1783 – 16 desember 1817) alias ‘Kapitan Poelo’ (Kapitan Pulau) – bukan oleh ‘Kapitan Pattimura’ (gelar yang diberikan kepada Thommas Matulessy oleh orang-orang yang menamakan dirinya, sebagai: “bangsa Indonesia”) – yang seperti “bernubuat” sebelum sang ajal datang menjemputnya di atas tiang gantungan: “kamu orang bisa bunuh beta, tapi skali klak akan bangkit Matulessy-Matulessy muda untuk melenyapkan gelap gulita yang menyelubungi kepulauan Maluku”[14].
Tetapi pada hari ini, mimpi Thomas Matulessy sebagaimana tersebut di atas, tidak kunjung terpenuhi, dan pekik perang Thomas Matulessy: “undure, undure, jangan undure, apa datang dari muka, jangan undure”, hanya menjadi pepesan kosong belaka[15]. Orang-orang Maluku lebih senang menenggelamkan diri mereka dalam keasyikan mempermasalahkan, agama, gelar, asal-usul, obor, ‘upacara’ (ceremony) bahkan wajah Thomas Matulessy – dan entah apalagi dari diri seorang Thomas Matulessy yang akan dipermasalahkan oleh mereka dikemudian hari – daripada berjuang mati-matian menghidupkan kembali “semangat perlawanan” Thomas Matulessy terhadap para penguasa Neofasis-Neofeodal-Neokolonial (Indonesia), dan daripada bekerja keras guna mewujudkan “harapan/cita-cita” Thomas Matulessy bagi Maluku yang berdaulat dan merdeka; tentram dan adil; aman dan damai; makmur dan sejahtera.
206 (dua ratus enam) tahun silam, Thomas Matulessy – yang belum genab berusia 35 (tiga puluh lima) tahun – bersama kawan-kawannya telah berani mengangkat senjata dengan menyabung nyawa mereka di medan tempur “melawan” bangsa Belanda, sehingga mereka layak/pantas/patut untuk disebut sebagai ‘pahlawan’ (pahlawan Maluku, dan bukan pahlawan Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh orang-orang yang menamakan diri mereka, sebagai: “bangsa Indonesia”).
Ironisnya – kalau kita tidak ingin menyebutnya sebagai sesuatu yang tragis – pada saat ini, orang Maluku hanya bisa membual di rumah-rumah kopi, mengobral kata-kata di dunia maya, dan mengemis sambil menitikkan air mata di ruang-ruang birokrasi para penguasa yang menamakan diri mereka, sebagai: “bangsa Indonesia”. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah sebutan paling layak/paling pantas/paling patut untuk diberikan kepada orang Maluku, baik di Belanda maupun di Indonesia dalam keadaan seperti yang sedang terjadi pada saat ini (?): “penakutkah?; pengecutkah?; pecundangkah?” – tetapi yang pasti, bukan pemberani, bukan pula pemenang, apalagi pahlawan.
Penulis menutup tulisan ini dengan mengangkat topi sebagai tanda ‘salut’ (salute) kepada Tuan Widji Thukul (1963-1998), seorang Bangsa ‘Jawa’ (Indonesia) yang keberaniannya melampaui keberanian orang-orang Bangsa ‘Alifuru’ (Maluku) yang paling berani sekalipun di abad XXI. Widji Thukul adalah seorang penyair yang berkata dalam sajaknya berjudul Peringatan – Pardi dalam puisinya dibawah judul, Sumpah Bambu Runcing – dan yang oleh penulis dikutip dalam tulisan ini: “Hanya ada satu kata: LAWAN!”.
Penulis merupakan Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Politeknik Negeri Ambon
Sumber:
[1]Kruls, H. J. (1960) The Strategic Importance in the World Picture of Present and Future. Los Angeles, the United States of America: California State College; Helfrrich, C. E. L. (1960) The Strategic Position. Los Angeles, the United States of America: California State College; Prins, J. (1960) Location, History, Forgotten Struggle. Los Angeles, the United States of America: California State College; Tichelman, G. L. (1960) Anthropological Aspects. Los Angeles, the United States of America: California State College; Bouman, Jan C. (1960) Social-Psychological Aspects. Los Angeles, the United States of America: California State College.
[2]Joesoef, Daoet (2011) Dasar Pembentukkan Bangsa. Di dalam: “Monarki Yogya” Inkonstitusional?. Jakarta: Kompas, h. 178; Joesoef, Daoet (2011) Pikiran & Gagasan Daoed Joesoef, 10 Wacana Tentang Aneka Masalah Kehidupan Bersama. Jakarta: Kompas, h. 179; Joesoef, Daoet (2014) Studi Strategi Logika Ketahanan Dan Pembangunan Nasional. Jakarta: Kompas, h. 171.
[3]Daradjadi (2014) MR. Sartono: Pejuang Demokrasi & Bapak Parlemen Indonesia. Jakarta: Kompas, h. 180.
[4]Adams, Cindy (2011) Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Jakarta: Yayasan Bung Karno & Media Pressindo, Ed. Rev., Cet. 2, h. 232; Kasenda, Peter (2015) Soekarno Di Bawah Bendera Jepang (1942-1945). Jakarta: Kompas, h. 120-121.
[5]Bartels, Dieter (2017) Di bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim – Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), jilid 2: Sejarah, Cet. 1, h. 665.
[6]Molen, Gesina Hermina Johanna van der (1960) The Legal Position According to International Law. Los Angeles, the United States of America: California State College; Cappello, N. J. C. M. Kapeyne van de (1960) Relation to the United Nations. Los Angeles, the United States of America: California State College.
[7]Roethof, Hendrik Jan (1960) An Existing State. Los Angeles, the United States of America: California State College; Pendapat para ahli hukum internasional yang tergabung dalam ‘Asosiasi Hukum Internasional Cabang Belanda’ (The Netherland’s Association for International Law (NAIL) / De Nederlandse Vereninging voor International Recht (NVIR)) di Rotterdam, Belanda pada hari sabtu, tanggal 24 Juni 1950; Keputusan Ketua Mahkamah Agung (De President van de Arrondissements-rechtbank) di Amsterdam, Belanda, pada hari kamis, tanggal 2 Nopember 1950; Keputusan Banding Mahkamah Tinggi di Amsterdam, Belanda, pada hari kamis, tanggal 8 pebruari 1951; Keputusan Mahkamah Agung (Raad van Justitie) di ‘Guinea Baru’ (New Guinea) pada hari jumat, tanggal 7 Maret 1952; Keputusan Mahkamah Agung (Raad van Justitie) di ‘Guinea Baru’ (New Guinea) pada hari sabtu, tanggal 3 Juli 1954;
[8]Parker, J. D. Karen (1996) Republik Maluku, The Case For Self-Determination (A Briefing Paper of ‘Humanitarian Law Project’ (HLP) / International Education Development (IED) and ‘Association of Humanitarian Lawyers’ (AHL)). Presented to The United Nations Commission on Human Rights 1996 Session, March, Geneva, Page: 1-17; Budiman, Hikmat (2019) Ke Timur Haluan Menuju (Studi Pendahuluan Tentang Integrasi Sosial, Jalur Perdagangan, Adat, Dan Pemuda Di Kepulauan Maluku). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, h. 43.
[9]Higgins, Noelle (2010) Regulating the Use of Force in Wars of National Liberation: The Need for a New Regime (A Study of the South Moluccas and Aceh). Leiden: Martinus Nijhoff Publishers; Higins, Noelle (2011) Opinion on the Status of the RMS. Expert Opinion. Dublin: tidak diterbitkan; Brabandere, Eric de (2011) Opinion on the Status of the RMS. Expert Opinion. Nederland: tidak diterbitkan.
[10]Missbach, Antje (2012) Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh, Suatu Gambaran tentang Konflik Separatis di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak, Sinopsis.
[11]de Fretes, Johannes Dirk (2007) Kebenaran Melebihi Persahabatan. Jakarta: Harman Pitalex & Kubuku, h. 39; Ir. Soekarno (2015) Dibawah Bendera Revolusi. Asvi Warman Adam: Sukarno Dalam Perjalanan Sejarah Bangsa. Jakarta: Yayasan Bung Karno & PT. Media Pressindo, Jilid I, Cet. 1, h. xviii.
[12]Preston, Martha L. Cottam, Tbeth Dietz-Uhler, Elena Mastors, Thomas (2012) Pengantar Psikologi Politik. Jakarta: Rajawali Pers, Ed. II, Cet 1, h. 327-328.
[13]Elson, Robert Edward (2009) The Idea of Indonesia, Sejarah Pemikiran dan Gagasan. Jakarta: Serambi, h. 2.
[14]Suyono, R. P. (2003) Peperangan Kerajaan Di Nusantara, Penelusuran Kepustakaan Sejarah. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, h. 178-191.
[15]Matulessy, Thomas (2022) Sejarah Asal Usul Pahlawan Nasional Kapitang Pattimura Anak Negeri Hulaliu. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, h. xi.