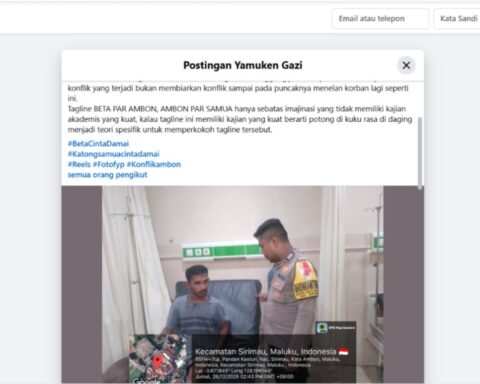Oleh: Ishak R. Boufakar – Anggota Penuh KAC 1995 Ambon
Selama 21 hari, Firdaus Ahmad Fauzi, pendaki asal Bogor, hilang di Gunung Binaya. Pada 17 Mei 2025, jasadnya ditemukan di Lembah Terjun Aimoto. Peristiwa itu mengguncang komunitas pecinta alam. Duka menjalar pelan, lalu berubah jadi gelombang ingatan. Teman-teman pendaki mulai membuka album lama—mengunggah foto, menulis kembali cerita-cerita yang nyaris usang, membagikan fragmen perjalanan yang pernah hidup.
Beta pun terseret dalam arus itu. Sebuah tulisan lawas terbit kembali dalam kepala: Pesan Cinta untuk Pegiat Gunung, dimuat di harian Identitas UNHAS, edisi 16 April 2016. Saat itu, Beta masih percaya bahwa mendaki gunung adalah ziarah jiwa. Jalan sunyi yang pernah dilalui Khadijah di Gua Hira untuk bertafakur, jalan yang dipilih Soe Hok Gie di Mahameru demi mencintai negeri ini secara utuh. Gunung, bagi Beta, adalah altar spiritual. Tempat jiwa ditempa dan nasionalisme tumbuh dalam keheningan.
Tapi belakangan, arah itu kabur. Pendakian berubah rupa. Dari ritual tafakur menjadi konten instan. Dari pengabdian sunyi menjadi panggung narsistik. Instagram menggantikan buku catatan. Feed menggantikan doa. Gunung tak lagi ditapaki, tapi dipajang. Tak lagi ditaklukkan, tapi dieksploitasi citranya.

Yang lebih getir: gunung kini bukan hanya kehilangan makna, tapi juga kehilangan rasa aman. Ia menjadi ruang kekerasan yang dibungkam. Pada 11 Mei 2025, DetikSulsel melaporkan kabar memilukan: seorang pendaki mencabuli anak perempuan berusia 12 tahun yang sedang mengalami hipotermia di Gunung Bawakaraeng. Gunung yang seharusnya menjadi pelukan hangat alam, berubah jadi tempat pengkhianatan.
Beta mulai bertanya ulang: ke mana perginya pendakian sebagai laku? Bukan sekadar rute menuju puncak, tapi perjalanan untuk mendewasakan jiwa, mengenal negeri, dan mencintai hidup dalam kesunyian yang agung.
Berikut ini adalah tulisan lama Beta—yang kini Beta sedikit pugar bahasanya—karena terasa lebih relevan dari sebelumnya. Semoga ia masih menyisakan jejak sunyi untuk direnungi.
Sebelum Gunung Dipajang
Jauh sebelum Instagram dibanjiri foto-foto gaya di puncak, gunung sudah lebih dulu menjadi tapal batas sakral—antara bumi dan langit, antara kefanaan dan keabadian. Ia bukan sekadar latar belakang swafoto, tapi ruang sunyi tempat manusia menyepi, menundukkan ego, dan menakar makna hidup dalam diam yang tinggi.
Anthoni de Vila menorehkan jejak awal pada 1495, ketika ia menaklukkan Aiguilla setinggi 2.097 meter di Prancis—satu langkah awal yang membawa manusia menatap langit dari dekat. Lalu Jan Carstensz, pada 1623, menembus dingin salju abadi di punggung Irian, dan namanya pun abadi sebagai mahkota Papua: Cartensz Pyramid. Sejarah terus mendaki, hingga pada 1953 Edmund Hillary dan Tenzing Norgay berdiri di atap dunia—membuat Everest tak lagi sekadar misteri, tapi altar tempat kemanusiaan merayakan keteguhan dan keberanian.
Gunung-gunung itu tak hanya dipanjat, mereka dilampaui sebagai ziarah manusia terhadap batasnya sendiri.

Khadijah dan Gunung Hira
Namun jauh sebelum semua itu, di abad ke-6 Masehi, seorang perempuan agung bernama Khadijah telah lebih dahulu menapaki Gunung Hira. Ia bukan pendaki dalam arti teknis seperti yang kita pahami hari ini, tetapi spiritualitasnya menjulang, melampaui ketinggian mana pun. Bersama suaminya, Muhammad bin Abdullah, Khadijah menyusuri jalur sunyi di lereng Hira, menghantarkan makanan dan kasih sayang kepada sang Nabi yang tengah tahanust—menyepi dari hiruk-pikuk dunia untuk mencari makna, mengakrabi sunyi, dan menautkan jiwa pada Yang Mahatinggi.
Bagi Khadijah, gunung bukan sekadar puncak yang menantang tubuh. Ia adalah ruang sakral, tempat di mana beban hidup bisa dilepaskan, jauh dari gelombang kekerasan dunia, dan sekaligus mendekat pada langit yang agung.
Dalam sunyi bebatuan Hira itulah, cinta menemukan bahasanya sendiri. Seperti yang ditulis Sibal Eraslan dalam Col ven Denzi, “Kekuatan hati dan cinta justru menjauhkan dari bahasa dan bicara. Gunung Hira mengajarkan kita untuk merasakan, bukan sekadar mendengarkan. Untuk hadir sepenuh hati, bukan hanya berbicara.”
Gie dan Mahameru
Dalam pandangan Khadijah, gunung bukanlah untuk ditaklukkan. Gunung adalah cermin jiwa—tempat menundukkan ego, membasuh kesombongan, dan menyuburkan doa. Sebuah perjalanan yang sesungguhnya adalah mendaki diri sendiri.
Berabad kemudian, semangat yang sama mengalir dalam darah seorang mahasiswa bernama Soe Hok Gie. Bagi Gie, pendakian bukan sekadar mengejar pemandangan indah, melainkan upaya mendalam untuk memahami dan mencintai Indonesia. Bersama Mapala UI, ia menjadikan gunung sebagai medan kontemplasi dan perlawanan, ruang untuk mengasah kesadaran dan menolak kepalsuan rezim Orde Lama.
Di tengah represi politik yang membungkam suara mahasiswa dan membekukan demokrasi, Gie menulis dalam catatan hariannya—yang kemudian diterbitkan LP3ES pascakematianya—bahwa cinta yang sehat hanya tumbuh dari pengenalan mendalam terhadap objeknya:
“Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal obyeknya. Dan mencintai Tanah Air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat… Karena itulah kami naik gunung.”
Pendakian menjadi lebih dari sebuah aktivitas fisik; ia adalah tindakan politik dan spiritual sekaligus.
Gie mendaki Mahameru, puncak tertinggi di Jawa Timur, dan di sanalah ajal menjemputnya—terpapar racun vulkanik pada tanggal 16 Desember 1969. Meski pergi di usia muda, semangatnya tetap menjulang tinggi, menginspirasi generasi berikutnya untuk memaknai pendakian lebih dari sekadar fisik, melainkan sebagai perjalanan spiritual dan perjuangan.
Pendakian Hari Ini
Kini, ketika puncak menjadi ajang pembuktian diri dan alam dijadikan latar estetika selfie, kita mulai bertanya: untuk apa sesungguhnya kaki-kaki ini mendaki? Gunung dipadati rombongan, namun sepi dari tafakur. Sampah menumpuk, hutan gundul, dan jejak langkah berujung pada luka ekologis. Krisis spiritual berjalan seiring krisis nasionalisme. Cinta pada tanah air berubah menjadi konsumsi estetika semu.
Kita terlupa bahwa pendakian adalah janji diam-diam: menjaga yang kita daki, bukan sekadar mencapai puncak. Gunung bukan trofi untuk dipamerkan, melainkan peringatan bahwa alam bukan objek semata, tapi subjek yang harus dihormati dan dilestarikan.

Pendakian Paling Agung
Barangkali sudah waktunya kita kembali mendaki dengan Khadijah dalam hati, dan Gie dalam langkah. Mencintai alam bukan lewat pose, tapi lewat pemeliharaan. Mengenal tanah air bukan dengan jargon, tapi dengan peluh dan empati. Karena seperti yang ditulis Harley Bayu Suta dalam Tarian Sang Kembara:
“Bagi kami, mengenal bumi pertiwi harus dekat dengan alamnya. Bagi kami, mencintai Nusantara harus kenal dengan masyarakatnya. Bagi kami, berbuat dan berkarya dengan kemampuan diri—itulah membangun negeri.”
Maka, sebelum mendaki lagi, pastikan hati ikut naik bersamamu. Bukan hanya tubuh.
Al-Fatihah untuk Para Pendaki yang Wafat di Gunung Binaya Untuk:
- Paul Claxton (1987)
- Fitra Wadiawari (2014)
- Amalia Sinarta Po (2017)
- Firdaus Ahmad Fauzi (2025)

“Langit Manusela menyimpan jejak langkah kalian. Aroma lumut, embun pagi, dan sunyi Lembah Aimoto akan terus menyebut nama-nama itu dalam senyap.”
Kami, Keluarga Besar Pecinta Alam dan masyarakat Maluku, turut berduka.
Semoga perjalanan kalian diterima sebagai pendakian paling agung—menuju cahaya.