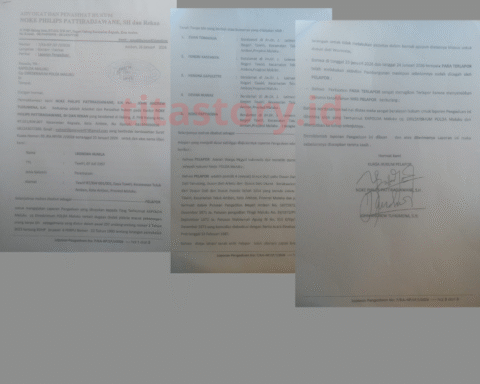Merauke, — Di tengah deru alat berat yang merobek hutan Papua, seorang tokoh adat berdiri tegak menghadang. Ambrosius Hairu, pemilik hak ulayat di wilayah Merauke, menancapkan sebuah salib di tanah yang sedang dibongkar. Isyarat itu tegas: hentikan aktivitas, ini tanah adat.
Aksi tersebut terjadi di kawasan hutan yang diklaim sebagai wilayah ulayat keluarga Ambrosius. Pembongkaran dilakukan oleh perusahaan yang disebut warga sebagai bagian dari PT Jhonlin Group, tanpa persetujuan masyarakat adat setempat. Video dan foto peristiwa itu dengan cepat menyebar di media sosial, memantik kemarahan publik dan solidaritas luas.

Bagi masyarakat adat Papua, salib yang ditancapkan Ambrosius bukan sekadar simbol keagamaan. Ia adalah tanda larangan adat, pernyataan sakral bahwa tanah tersebut tidak boleh disentuh tanpa musyawarah, tanpa izin, dan tanpa persetujuan pemilik ulayat.
Papua Bukan Tanah Kosong
Lembaga Bantuan Hukum Papua Merauke menyatakan bahwa aktivitas pembongkaran hutan diduga dilakukan secara sepihak. Tidak ada proses konsultasi, musyawarah adat, maupun persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) prinsip yang seharusnya menjadi dasar setiap proyek di wilayah masyarakat adat Papua.
“Papua bukan tanah kosong. Setiap jengkal tanah ada pemilik adatnya,” tulis LBH Papua Merauke dalam keterangan yang beredar di media sosial.
Prinsip tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yang mengakui dan melindungi hak ulayat masyarakat adat. Namun, dalam praktik, pengakuan hukum kerap kalah oleh kepentingan investasi berskala besar.
Hutan sebagai Sumber Hidup
Gelombang dukungan terhadap Ambrosius Hairu terus mengalir. Ribuan warganet menyuarakan pesan yang sama: tanah dan hutan adalah identitas orang Papua.
“Hutan itu dapur hidup kami. Kami bisa hidup tanpa uang, tapi tidak tanpa tanah,” tulis seorang warganet dalam kolom komentar unggahan video aksi tersebut.
Bagi masyarakat adat Papua, hutan bukan sekadar aset ekonomi. Ia adalah ruang hidup, sumber pangan (sagu, berburu), obat-obatan, serta pusat relasi spiritual dengan leluhur. Pembongkaran hutan berarti pemutusan rantai hidup lintas generasi.
Kasus di Merauke ini menambah daftar panjang konflik agraria di Papua. Dalam satu dekade terakhir, proyek-proyek berbasis perkebunan, kehutanan, dan pangan skala besar kerap masuk ke wilayah adat dengan dalih pembangunan dan ketahanan nasional. Namun, di lapangan, masyarakat adat sering kali hanya menjadi penonton—atau korban.
Aksi Ambrosius Hairu kini dipandang sebagai simbol perlawanan moral terhadap ekspansi korporasi yang mengabaikan dimensi sosial, kultural, dan spiritual masyarakat adat.
“Ini bukan anti pembangunan,” kata seorang aktivis lingkungan Papua. “Ini soal siapa yang menentukan masa depan tanah Papua: rakyat adat atau pemodal.”
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Jhonlin Group belum memberikan pernyataan resmi terkait penghentian aktivitas alat berat maupun tudingan pelanggaran hak ulayat. Sementara itu, desakan publik agar pemerintah daerah dan pusat turun tangan kian menguat.
Masyarakat sipil meminta negara hadir bukan sebagai fasilitator investasi semata, melainkan sebagai pelindung hak konstitusional masyarakat adat.
Penancapan salib di tengah hutan Merauke menjadi pengingat keras: di Papua, konflik agraria bukan sekadar sengketa lahan, melainkan pertarungan atas martabat, identitas, dan hak hidup sebuah bangsa adat.