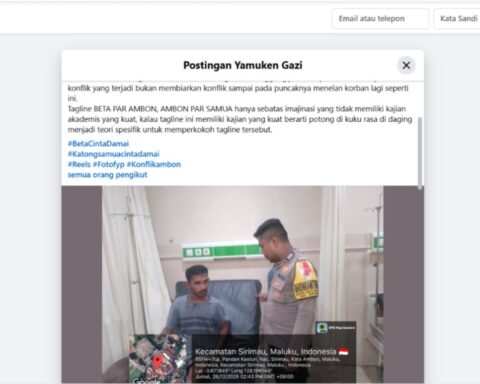Kupang, Nusa Tenggara Timur,— Gugatan warga Poco Leok terhadap Bupati Manggarai kembali memasuki babak krusial. Dalam sidang pembuktian kedua di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, warga menyerahkan bukti tambahan yang mengungkap dugaan penghalang-halangan kebebasan berekspresi, intimidasi aparat pemerintah daerah, hingga kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang menolak proyek panas bumi (geothermal) di Poco Leok.
Sidang yang digelar pada 18 Desember 2025 itu merupakan bagian dari perkara Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)yang diajukan Agustinus Tuju, warga Poco Leok, terhadap Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit, dengan register perkara Nomor 26/G/TF/2025/PTUN.KPG.

Bukti Tambahan: Penolakan Adat hingga Intimidasi di Kantor Bupati
Kuasa hukum penggugat dari Koalisi Advokasi Poco Leok, Judianto Simanjuntak, menjelaskan bahwa agenda persidangan kali ini difokuskan pada pengajuan tambahan bukti surat dari kedua belah pihak.
Menurut Judianto, bukti yang diajukan warga mencakup beberapa aspek penting:
- Dokumen penolakan resmi Masyarakat Adat 10 Gendang Poco Leok terhadap proyek geothermal,
- Bukti kriminalisasi dan tekanan hukum terhadap warga yang menolak proyek,
- Dokumentasi intimidasi dan penghalang-halangan aksi damai warga di Kantor Bupati Manggarai pada 5 Juni 2025,
- Serta bukti kerugian materiil yang dialami Agustinus Tuju akibat tindakan pemerintah daerah.
“Bukti-bukti ini menunjukkan adanya praktik sistematis yang mempersempit ruang demokrasi masyarakat adat Poco Leok,” kata Judianto usai sidang.

Video Tergugat Dinilai Justru Memperkuat Gugatan Warga
Dalam persidangan yang sama, pihak tergugat—Bupati Manggarai—mengajukan bukti elektronik berupa video aksi warga Poco Leok pada 5 Juni 2025, yang kemudian diputar di hadapan majelis hakim.
Namun, menurut kuasa hukum penggugat, video tersebut justru memperlihatkan kegagalan kepala daerah dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.
“Alih-alih menyerap aspirasi, video itu menunjukkan bagaimana Bupati Manggarai melakukan ancaman verbal yang membuat warga ketakutan. Ini bertentangan dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan kepala daerah mengembangkan kehidupan demokrasi dan partisipasi publik,” tegas Judianto.
Ia juga membantah klaim tergugat yang menyebut orasi warga sebagai bentuk penghinaan. Menurutnya, ekspresi warga merupakan luapan kekecewaan akibat tertutupnya ruang dialog resmi, sehingga demonstrasi menjadi satu-satunya saluran aspirasi yang tersedia.
“Justru di sinilah terlihat adanya penyempitan ruang demokrasi oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

WALHI dan Solidaritas Perempuan: Ini Soal Ruang Hidup dan Hak Konstitusional
Kepala Divisi Advokasi WALHI NTT, Gres Gracelia, menegaskan bahwa perkara Poco Leok tidak bisa dipandang semata sebagai konflik hukum individual.
“Ini adalah perjuangan menjaga ruang hidup masyarakat Manggarai, Flores, dan NTT secara keseluruhan. Pembungkaman dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat adalah bentuk penghancuran identitas dan hak hidup,” kata Gres.
Sementara itu, Linda Tagie, Ketua BEK Solidaritas Perempuan Flobamoratas, menyoroti keterlibatan perempuan dalam barisan perlawanan Poco Leok.
“Demonstrasi ini lahir karena jalur-jalur formal ditutup. Perempuan berdiri di garis depan karena relasi mereka dengan tanah, air, pangan, dan tradisi sangat erat. Ancaman terhadap perempuan Poco Leok adalah ancaman terhadap seluruh gerakan pembela HAM,” ujarnya.
Linda menegaskan bahwa negara wajib melindungi masyarakat adat yang mempertahankan ruang hidupnya. Setiap upaya menghalangi aksi damai, menurutnya, merupakan pelanggaran hak konstitusional.
Kuasa hukum lainnya, Marthen Salu, menyampaikan bahwa persidangan akan berlanjut pada 8 Januari 2026, dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak penggugat, yakni warga Poco Leok yang mengalami langsung peristiwa penghalang-halangan aksi damai.
Setelah itu, majelis hakim akan mendengarkan saksi dari tergugat, dilanjutkan keterangan ahli dari kedua belah pihak.
“Perkara ini masih panjang, tetapi satu hal jelas: publik perlu terus mengawal agar ruang demokrasi dan hak masyarakat adat tidak dikorbankan atas nama proyek pembangunan,” kata Marthen.