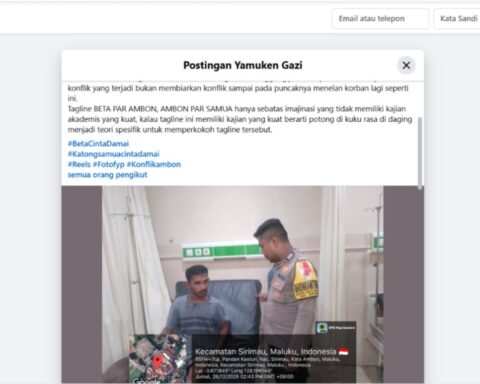Yogyakarta, — Ruang diskusi yang semestinya menjadi tempat aman bagi pertukaran gagasan kembali mendapat tekanan. Diskusi buku “Pembangunan untuk Siapa? Kisah Perempuan di Kampung Kami” yang digelar Konde.co bersama Marjin Kiri dan didukung Trend Asia di Yogyakarta, Senin, 22 Desember 2025, didatangi aparat kepolisian sebanyak dua kali—sebelum dan saat acara berlangsung.
Aparat mempertanyakan izin keramaian dan meminta kejelasan legalitas acara. Padahal, diskusi berlangsung tertutup, tanpa pengerahan massa, dan di ruang privat. Polisi tetap berada di lokasi hingga acara selesai, memantau jalannya diskusi dari awal hingga akhir. Bagi penyelenggara, kehadiran tersebut bukan sekadar administratif, melainkan bentuk pengawasan berlebihan yang berpotensi intimidatif.
Diskusi Buku Diposisikan sebagai “Keramaian”
Pada sore hari sebelum diskusi dimulai, sejumlah aparat mendatangi lokasi dan menanyakan apakah panitia telah mengajukan izin keramaian. Polisi menyatakan kegiatan diskusi buku wajib mengantongi izin atau setidaknya dilaporkan kepada aparat keamanan.
Pernyataan ini langsung dipersoalkan oleh penyelenggara. Diskusi buku bukan unjuk rasa, bukan pawai, dan bukan rapat umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang tersebut secara limitatif hanya mengatur demonstrasi, mimbar bebas, pawai, dan rapat umum—bukan forum diskusi pengetahuan.
“Diskusi publik adalah hak konstitusional warga negara, bukan objek perizinan aparat keamanan,” demikian pernyataan sikap Konde.co, Marjin Kiri, dan Trend Asia, dalam rilis yang diterima titastory.id, Rabu (24/12).
Tak Ada Dasar Hukum, Tapi Pengawasan Tetap Berjalan
Penyelenggara menilai permintaan izin tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah. Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945 menjamin kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat. Pasal 28F menjamin hak untuk mencari dan menyampaikan informasi.
Jaminan itu diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005.
Bahkan jika merujuk Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2023, aturan tersebut ditujukan untuk kegiatan keramaian umum berskala besar yang berpotensi mengganggu ketertiban. Diskusi buku di ruang tertutup dengan peserta terbatas jelas tidak memenuhi kriteria itu.
Namun demikian, aparat tetap berada di lokasi hingga diskusi berakhir. Bagi penyelenggara, tindakan ini menciptakan tekanan psikologis dan rasa tidak aman, baik bagi panitia maupun peserta.
Ancaman bagi Kebebasan Akademik dan Demokrasi
Konde.co, Marjin Kiri, dan Trend Asia menilai praktik ini sebagai preseden berbahaya. Jika diskusi buku saja dipantau dan dimintai izin, maka ruang berpikir kritis warga negara perlahan dipersempit.
“Ini bukan sekadar persoalan administratif, tapi soal pembungkaman pengetahuan kritis,” tulis mereka.
Pengawasan aparat terhadap diskusi buku dinilai memperlihatkan kecenderungan negara memandang aktivitas berpikir, membaca, dan berdiskusi sebagai potensi ancaman. Logika semacam ini mengingatkan pada praktik otoritarian masa lalu, ketika negara hadir bukan sebagai pelindung kebebasan, melainkan sebagai pengawas pikiran.
Buku “Pembangunan untuk Siapa? Kisah Perempuan di Kampung Kami” sendiri merekam pengalaman perempuan di berbagai wilayah Indonesia yang terdampak pembangunan nirpartisipatif—mulai dari penggusuran, perampasan ruang hidup, hingga kehancuran ekologi akibat proyek-proyek besar seperti Proyek Strategis Nasional, ekspansi industri ekstraktif, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Buku ini menghadirkan pengalaman perempuan sebagai pengetahuan politik, menantang narasi pembangunan arus utama yang maskulin, teknokratis, dan kolonial. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap diskusi buku dipandang tidak netral.
“Suara perempuan akar rumput kerap dianggap mengganggu, sehingga diawasi, bukan didengar,” tulis penyelenggara.
Diskusi tetap berjalan hingga selesai. Namun penyelenggara menegaskan penolakan terhadap segala bentuk intimidasi dan pengawasan berlebihan di ruang diskusi sipil.
Negara, menurut mereka, seharusnya menjamin ruang aman bagi pertukaran gagasan—bukan justru menciptakan rasa takut. Jika praktik ini dibiarkan, demokrasi akan tergerus bukan oleh larangan terbuka, melainkan oleh normalisasi pengawasan.
“Kemerdekaan adalah hak segala bangsa—termasuk kemerdekaan berpikir dan berbicara tanpa diawasi,” tegas pernyataan bersama Konde.co, Marjin Kiri, dan Trend Asia.