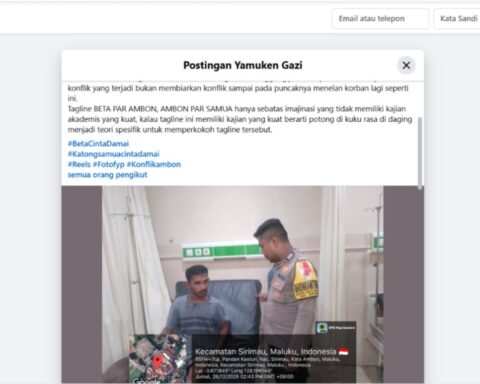Di balik janji swasembada Presiden Prabowo, tanah adat kembali terancam kepentingan investor
Jakarta, — Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Selasa, 16 Desember 2025, dibingkai sebagai langkah percepatan pembangunan di enam provinsi Papua. Namun, di balik bahasa resmi tentang kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian nasional, pertemuan itu justru memunculkan kegelisahan lama yang tak pernah benar-benar padam: siapa yang diuntungkan dari pembangunan Papua, dan siapa yang kembali dikorbankan?
Pertemuan tersebut dihadiri enam gubernur, 42 bupati dan wali kota, serta jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Di hadapan mereka, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengamanan kekayaan negara, swasembada pangan, dan terutama swasembada energi. Papua, dengan cadangan sumber daya alam yang melimpah, disebut sebagai salah satu kawasan strategis nasional untuk menopang agenda itu.

Bagi pemerintah pusat, narasi ini adalah kelanjutan dari visi besar kemandirian ekonomi. Namun bagi banyak orang Papua, kata “kawasan strategis” justru menghidupkan kembali trauma lama: pembukaan ruang hidup adat untuk investasi skala besar, dari tambang, energi, hingga proyek infrastruktur raksasa.
Presiden juga menyinggung percepatan pembangunan infrastruktur dasar rumah sakit, sekolah rakyat, fasilitas pendidikan umum, pariwisata, serta peningkatan keamanan. Janji-janji itu terdengar familier. Sejak Otonomi Khusus Papua diberlakukan lebih dari dua dekade lalu, daftar program serupa berulang kali disampaikan dalam forum resmi. Namun, kesenjangan sosial, konflik agraria, dan kekerasan struktural tak pernah benar-benar surut.
Di titik inilah sentimen kegagalan Otsus kembali menguat. Banyak kalangan menilai Otsus gagal menjalankan mandat utamanya: melindungi hak dasar masyarakat adat Papua atas tanah, sumber daya alam, dan martabat hidup. Dana triliunan rupiah mengalir, tetapi tidak dibarengi dengan penguatan posisi politik dan hukum masyarakat adat dalam menghadapi negara dan korporasi.
Penekanan Presiden pada “pengamanan kekayaan negara” dan swasembada energi dinilai membuka ruang lebar bagi masuknya investor besar. Dalam praktiknya, agenda semacam ini kerap diterjemahkan menjadi proyek pertambangan, migas, panas bumi, atau pembangkit listrik skala besar—yang hampir selalu beririsan dengan tanah ulayat. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup, identitas, dan relasi spiritual yang tak tergantikan.
Kekhawatiran semakin besar karena sejarah menunjukkan bahwa proyek-proyek strategis nasional di Papua kerap berjalan tanpa persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) dari masyarakat adat. Proses konsultasi sering bersifat formalitas, sementara aparat keamanan diturunkan untuk “mengamankan” investasi. Di banyak tempat, konflik agraria berujung kriminalisasi warga, pengungsian, bahkan korban jiwa.
Di tengah situasi ini, agenda percepatan pembangunan yang digembar-gemborkan pemerintah pusat justru dibaca sebagian kalangan sebagai babak baru kolonisasi ekonomi. Papua tidak lagi sekadar wilayah yang “tertinggal”, tetapi ladang energi dan sumber daya yang harus diamankan demi kepentingan nasional. Pertanyaannya: nasional versi siapa?
Pertemuan di Istana itu mungkin dimaksudkan sebagai konsolidasi. Namun bagi masyarakat adat Papua, ia justru menjadi pengingat bahwa arah pembangunan masih ditentukan dari Jakarta, dengan logika keamanan dan investasi sebagai panglima. Selama Otsus tidak dibenahi secara mendasar—dengan menempatkan hak masyarakat adat sebagai fondasi, bukan penghalang—Papua akan terus berada di persimpangan: antara janji kesejahteraan dan kenyataan kehilangan tanahnya sendiri.
Di era Presiden Prabowo, swasembada energi diproyeksikan sebagai simbol kedaulatan bangsa. Namun di Papua, kedaulatan itu diuji oleh satu pertanyaan mendasar: apakah negara bersedia mengakui bahwa tanpa keadilan bagi masyarakat adat, tidak ada pembangunan yang benar-benar berdaulat?