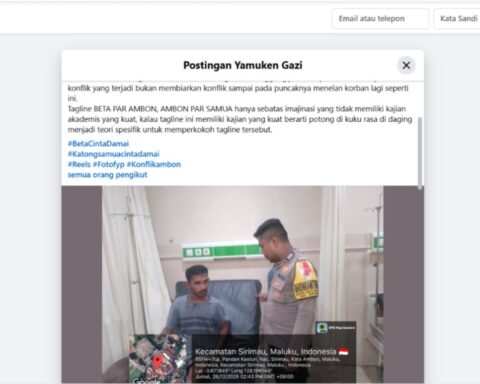Oleh: Udin Najil, Doyan Kajian Media dan Budaya
Ambon,– Setelah beberapa hari mengamati pemberitaan konflik melalui media sosial yang terjadi di Stain, Kota Ambon, saya terperangah dengan sebuah pemberitaan sehubung yang dibagikan oleh seorang jurnalis kawakan di laman facebooknya. Jurnalis tersebut kelihatannya hendak mengkritisi pemberitaan konflik yang menurutnya tidak etis dari sebuah media daring lokal, karena mungkin, terlalu provokatif. Sebagai pembaca, saya barangkali akan sepakat dengannya.
Dalam dunia jurnalistik, pilihan judul bisa mengundang atensi selama ia sensasional. Judul bisa menentukan apakah berita tersebut menjadi komoditas yang laku di pangsa pasar pembaca atau tidak. Selain itu, judul juga bisa mendefinisikan dan membatasi pandangan. Penggalan judul “Ambon Memanas” secara leksikon, bisa berakibat fatal dalam konteks sosial-budaya orang Maluku, khususnya Kota Ambon yang kerap kali diwarnai konflik kelompok sejak dulu.
Antropolog Patricia Spyer dalam Fire Without Smoke and Other Phantoms of Ambon’s Violence: Media Effects, Agency, and The Work of Imagination (2002) menyebut jika konflik dan media di Kota Ambon punya hubungan yang dialektis. Dalam masa maupun pasca konflik sejak 1999-2000an, media yang diproduksi kedua belah pihak (meski terbatas pada televisi dan VCD) bisa sebagai alat untuk membentuk narasi dan identitas antar kelompok yang berkonflik. Media-media ini kerap kali memperkuat perpecahan dan stereotipe.
Namun, dalam tulisan ini, saya tidak hendak membahas dengan menguntungkan salah satu kelompok. Mengingat, meminjam kalimat Spyer, Maluku pernah menjadi “kolam konsentrasi rasa sakit dan kepahitan”. Sebagai orang yang berada di luar konflik, saya paham posisi dan berharap sebagaimana mereka yang juga menginginkan kedamaian dan ketentraman. Justru di sini, saya hanya akan menyoroti gelagat media yang mendramatisir masalah, dan diam-diam mengambil keuntungan dari pemberitaan konflik, baik ekonomi dan politik.
Konflik Sebagai Komoditas
Pasca Perang Dunia Pertama, rekan Lord Northcliffe, jurnalis Inggris sekaligus pendiri The Daily Mail dan The Times berkomentar bahwa “perang tidak hanya menciptakan pasokan berita, tetapi juga permintaan akan berita tersebut. Begitu mengakarnya daya tarik perang dan segala hal yang berkaitan dengannya sehingga…sebuah surat kabar hanya perlu memasang plakat ‘Pertempuran Besar’ agar penjualannya meningkat” (Laswell, 1938: 192).
Misalnya, selama Perang Teluk, berbagai surat kabar di Amerika, termasuk Cable News Network (CNN) menikmati peningkatan sirkulasi. Namun, disini saya tidak mencoba membandingkan keuntungan yang diperoleh media pada pemberitaan konflik skala besar, dengan konflik komunal yang terjadi di Stain dengan skala yang lebih kecil dan terukur. Ini jelas tidak sebanding. Tapi saya menangkap benang merah dalam pemberitaan konflik, baik skala besar maupun kecil, yakni konflik sebagai komoditas.
Di mata media, semua bisa menjadi komoditas selama ia punya nilai jual, termasuk konflik itu sendiri. Sebagai contoh, pemberitaan konflik dengan judul sensasional seperti “Ambon Memanas, Fredi Moses Desak Pemkot Cari Solusi Baru: Proses Hukum Tidak Sentuh Akar Masalah” (28/11/2025) alih-alih mempertimbangkan konsekuensi, justru menciptakan kesan darurat atau konflik untuk menarik klik dan perhatian pembaca (clickbait). Pemberitaan konflik dengan sensasi dan drama, tidak saja mempertinggi sirkulasi namun juga meningkatkan pendapatan iklan dan viewership.
Contoh yang lain bagaimana media mengambil keuntungan dari konflik, bisa ditelisik dari atensi media lokal yang memberitakan secara ramai-ramai klarifikasi pernyataan kontroversi Walikota Ambon, Bodewin Wattimena soal “Pulang Kampung” dari laman Facebooknya. Sebagai elit lokal, pernyataannya cukup menyinggung, apalagi dalam masa konflik yang berlangsung. Dalam hal ini, saya sepakat di lain sisi pemberitaan klarifikasi tersebut, namun tidak di sisi lain. Mengapa? Selain karena pernyataannya bisa mengalihkan perhatian pada penyelesaian konflik, ia malah dijadikan sebagai clickbait.
Clickbait itu mengacu pada konten yang tujuannya untuk menarik perhatian dengan mendorong pembaca/pengunjung untuk mengklik tautan ke halaman web tertentu (Chen dkk, 2015). Dalam pemberitaan konflik, clickbait menunjukan motivasi ekonomi secara gamblang. Ia mencerminkan kedangkalan media dalam menguraikan konflik secara kritis. Hal ini dapat kita amati pada beberapa pemberitaan konflik yang kurang menganalisis konteks secara investigasi–melihat konflik komunal secara holistik dengan pertimbangan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis, serta memperlihatkan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dinamika konflik, alih-alih sekedar pemberitaan seperlunya.
Nebeng Citra Elit Lokal
Sialnya, pemberitaan konflik seperlunya ini pun didramatisasi oleh media dengan memberi tempat pada elit lokal untuk menunjukan sisi empatinya pada konflik. Di Maluku, khususnya Kota Ambon, pencitraan elit lokal di media tidak bisa dianggap sepele. Wajah-wajah elit lokal ini beserta ucapan-ucapan selamat yang memenuhi dasbor media tidak bisa dibaca sebagai hubungan bisnis semata, tapi juga politik. Media dan elit lokal memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Media membantu membranding sosok, dan elit lokal memasang iklan.
Elit lokal bisa berupa banyak subjek. Mereka bisa diidentifikasi sebagai pemilik modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik dalam pengertian Bourdieu. Pada pemberitaan konflik, elit-elit lokal ini di servis, diberikan ruang oleh media untuk merespon konflik yang ada. Mereka seolah dihadirkan untuk terlibat dalam narasi konflik dengan menghadirkan pernyataan yang empati, bersikap objektif tetapi sarat politik, pengulangan, dan dangkal.
Dalam bab Sourcing Mass-Media News: The Third Filter di buku Manufacturing Consent The Political Economy of the Mass Media yang ditulis Edward S. Herman dan Noam Chomsky (1988), pemilihan narasumber merupakan keputusan ekonomi-politik media. Pemilihan narasumber tidak pernah netral, ia selalu disusupi kepentingan tertentu.
Perhatikan beberapa pemberitaan di bawah ini: “Rovik Minta Polsek Kebun Cengkih Dibentuk, Upaya Mitigasi Konflik Berulang” (27/11/2025), “DPRD Maluku Desak Polda Sikat Pelaku Penganiayaan, Solichin: Segera Amankan Titik Rawan” (28/11/2025), “Ketua KNPI Ambon Tegaskan Pesan Wali Kota: Hargai Perbedaan, Jangan Provokasi Kota Ini” (27/11/2025). Apa yang baru dari keempat berita ini? Jawabannya, tidak ada. Pernyataan elit lokal seperti ini sebetulnya hanya pengulangan yang tidak perlu. Pernyataan solutif narasumber yang diambil untuk menghiasi masa konflik sudah menjadi pernyataan klise. Namun, mengapa tanpa mereka tetap diberikan ruang dalam pemberitaan konflik?
Ada dua jawaban untuk ini: pertama, pada elit lokal yang termuat pada pemberitaan satu dan dua, tentu memiliki empat jenis modal yang bisa digunakannya untuk memperpetuasi citranya di media, selain modal budaya (kompeten), modal ekonomi (iklan) maupun modal sosial (koneksi) dengan pemilik media, juga bisa menjadi faktor yang lain. Tentu karena ini hubungan timbal balik yang menguntungkan.
Kedua, platform yang baru terjun dalam dunia media tentu membutuhkan narasumber yang punya modal budaya dan modal sosial untuk sirkulasi pemberitaannya. Ia membantu menghubungkan media dengan sejawat-sejawat narasumber. Hal ini bisa dilihat pada pemberitaan konflik ketiga di atas. Sebagai gantinya, narasumber–karateker KNPI yang mencitrakan Walikota Ambon, mesti dicitrakan, dibingkai, diservis kembali oleh media sebagai bagian dari mereka yang diklaim kredibel dan kompeten (merangkak menjadi elit lokal) untuk diterima pembaca.
Pola pemberitaan konflik di Stain oleh media lokal kiranya terjebak pada pembingkaian yang sama, yakni menempatkan elit lokal sebagai narasumber yang kredibel, bukan korban dari kelompok yang bertikai. Anggapan media seperti ini justru memperlihatkan gelagat media yang malas, dangkal, dan tidak kritis atas konflik yang terjadi.
Mengapa? Mengingat Herman dan Chomsky, “mengambil dari sumber yang dianggap kredibel mengurangi biaya investigasi, sedangkan materi dari sumber yang tidak kredibel informasi secara prima facie, atau yang akan memicu kritik dan ancaman, memerlukan pemeriksaan yang teliti dan penelitian yang mahal” (hlm,20). Makanya alih-alih menjadi kritis, media-media lokal di Ambon malah serupa salon yang doyan memolesi citra wajah para elit lokal demi keuntungan ekonomi-politik medianya.