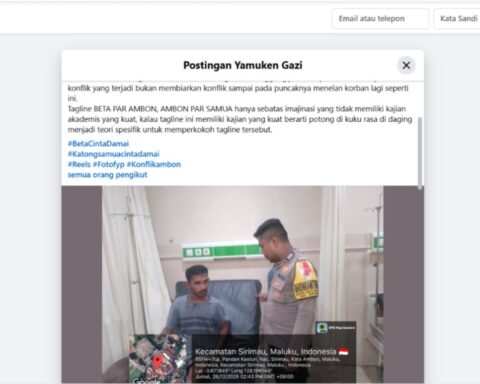Ambon, — Delapan dekade setelah konstitusi Indonesia mengakui keberadaan masyarakat adat, realitas di lapangan menunjukkan arah sebaliknya: hak adat terus dirampas, ruang hidup menyempit, dan masyarakat adat di Maluku makin terpinggirkan. Kondisi ini mengemuka dalam Konsolidasi dan Diskusi Publik RUU Masyarakat Adat yang digelar Koem Telapak bersama Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat di Ambon, Selasa (2/12/2025).
Perempuan adat dari Suku Nuaulu, Hunanatu Matoke, menegaskan bahwa pengakuan negara hanya berhenti di atas kertas. “Negara mengakui kami sejak 80 tahun lalu, tetapi hak kami dirampas dan kami tidak diberi kesempatan menentukan apa yang terbaik bagi kami,” ujarnya.
Di tengah ekspansi industri ekstraktif, konversi hutan, dan perubahan iklim, masyarakat adat menjadi kelompok yang paling pertama dan paling parah merasakan dampak: kehilangan tanah ulayat, rusaknya lingkungan, hilangnya sumber penghidupan, hingga terkikisnya tatanan adat dan budaya yang menopang kehidupan mereka.

Di Maluku, sebagian besar masyarakat adat tinggal di pesisir, pulau-pulau kecil, hingga wilayah 3T. Negeri adat dipimpin oleh raja dan seluruh pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah adat.
Namun ketika wilayah adat berubah menjadi kawasan industri, negara dinilai gagal melindungi hak-hak dasar mereka.
Sekretaris Majelis Latupati Maluku, Decky Tanasale, menjelaskan bahwa praktik adat di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan masih sangat kuat. Hukum adat digunakan menyelesaikan hampir semua masalah, termasuk perkara pidana.
Meski hampir seluruh desa di Maluku adalah negeri adat, hanya tiga yang teregistrasi di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA): Paperu, Tananahu, dan Haruku. Hambatan birokrasi, minimnya pendataan, dan kurangnya dukungan pemerintah membuat sebagian besar wilayah adat belum diakui secara hukum.
Sementara itu, stigma seperti “suku terasing”, “terbelakang”, atau “tidak berpendidikan” masih dilekatkan pada masyarakat adat—menambah lapisan diskriminasi yang mereka alami.
Nasib Perempuan Adat
Persoalan kian kompleks bagi perempuan adat. Sistem adat yang maskulinitas menempatkan laki-laki sebagai penentu kebijakan, sementara perempuan hanya dilibatkan dalam pekerjaan domestik atau peran tradisional.
Apriliska Titahena dari Lumah Ajare menyebutkan bahwa minimnya keterlibatan perempuan berdampak langsung pada layanan dasar: akses air bersih, sanitasi, hingga kebutuhan kesehatan reproduksi.
Di beberapa wilayah, seperti Kepulauan Tanimbar dan Aru, kasus kekerasan seksual masih diselesaikan dengan denda adat, tanpa mempertimbangkan hak korban. “Hukum adat sering kali tidak berpihak pada perempuan,” kata Lusi Peilow dari Gerak Bersama Perempuan Maluku.
Penjaga Hutan yang Terpinggirkan
Meski menghadapi diskriminasi, masyarakat adat justru menjadi garda depan penyelamat lingkungan. Mereka mempertahankan praktik tradisional, seperti sistem sasi, yang menjaga keseimbangan ekosistem laut dan hutan.
“Sasi adalah bukti nyata bagaimana masyarakat adat menjaga alam,” kata Elisa Laiuluy dari Barisan Pemuda Adat SBB.
Namun tekanan industri telah lama menghantam mereka. Puncaknya terjadi pada era Orde Baru ketika hutan Pulau Seram digunduli untuk industri kayu lapis sejak 1985. Konflik di Pulau Romang, penolakan Save Aru, hingga kriminalisasi masyarakat adat menunjukkan pola berulang: negara berpihak pada investasi, bukan pada rakyat adat.
Pada diskusi ini, Koem Telapak dan Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mendesak agar RUU yang telah tertunda 15 tahun segera disahkan. Undang-undang ini dinilai menjadi satu-satunya instrumen yang dapat memperkuat pengakuan, perlindungan, dan pemulihan hak masyarakat adat.
Kegiatan yang berlangsung bertepatan dengan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) ini juga menegaskan pentingnya peran perempuan adat dalam mendorong perubahan.
Joan Pesulima dari AJI Ambon menekankan peran media: “Isu masyarakat adat harus menjadi isu nasional. Media perlu mengubah perspektif: masyarakat adat bukan suku terasing, mereka warga negara dengan tatanan sosial yang dinamis.”