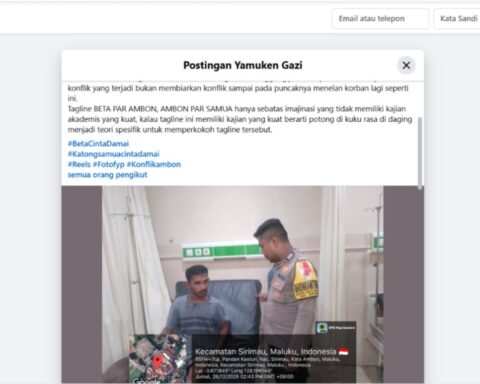Belém, Brasil, — Suara perlawanan Masyarakat Adat menggema di jalan-jalan Belém. Puluhan ribu Masyarakat Adat dan aktivis lingkungan dari seluruh dunia turun ke jalan, Sabtu (15/11/2025), menuntut penghentian solusi palsu iklim serta pelibatan penuh dalam perundingan COP30. Aksi ini menjadi mobilisasi terbesar sejak 2021, setelah tiga COP sebelumnya membatasi ruang demonstrasi masyarakat sipil.
Di bawah matahari Amazon, mereka membentang spanduk bertuliskan “The Answer is Us”—pesan tegas bahwa tidak ada solusi iklim yang layak tanpa perlindungan wilayah adat dan pengetahuan tradisional yang telah menjaga hutan, sungai, gunung, dan laut selama berabad-abad.
Setidaknya 30 ribu Masyarakat Adat hadir dari seluruh dunia, termasuk delegasi kuat dari Nusantara dan Papua. Mereka menuntut penghentian ekspansi energi fosil, perlindungan hutan adat, penghentian kriminalisasi pembela lingkungan, serta jaminan partisipasi bermakna dalam seluruh agenda iklim global.

Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi menegaskan bahwa hingga pekan pertama COP30, ruang negosiasi masih mengabaikan tuntutan Masyarakat Adat.
“Mereka terus mengingkari ilmu pengetahuan: siapa penjaga hutan terbaik? Masyarakat Adat,” katanya. Ia menyebut COP30 masih dikuasai kepentingan industri, khususnya setelah laporan KBPO menyebut 1.600 pelobi energi fosil hadir di arena COP.
Hutan Adat Dikorbankan, Transmigrasi Dihidupkan
Masyarakat Adat Papua ikut berunjuk rasa sambil membawa spanduk:
“West Papua Is Not an Empty Land. Save Our Indigenous Forest.”
Pesan ini merespons percepatan konversi hutan Papua untuk kepentingan komersial—sawit, tebu bioetanol, tambang, hingga food estate yang menggerus wilayah adat dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat kampung.
Direktur Yayasan Pusaka, Franky Samperante, menegaskan “Negara terus melihat hutan Papua hanya sebagai komoditas. Pola ini mendorong deforestasi besar-besaran.”
Situasi Papua mendapat perhatian serius dari Pakar HAM PBB, yang dalam pernyataan resminya (4/11/2025) mengecam revisi UU Otsus Papua karena memusatkan kekuasaan dan mengikis tata kelola adat. Mereka juga menyoroti kebangkitan program transmigrasi yang berpotensi mempercepat penghapusan budaya asli dan perubahan demografi Papua secara sistematis.
“Transmigrasi di Papua Barat mempercepat asimilasi paksa dan mengurangi jumlah Masyarakat Adat yang hidup di tanah leluhurnya,” tulis para ahli HAM PBB.
Masyarakat Adat Menjadi Penentu Solusi, Bukan Objek Korban Kebijakan
Dalam COP30, kehadiran lebih dari 3.000 pemimpin adat dunia merupakan yang terbesar sepanjang sejarah konferensi. Menteri Masyarakat Adat Brasil, Sonia Guajajara, menyatakan bahwa Masyarakat Adat bukan hanya korban krisis iklim, tetapi pemegang kunci solusi.
“Solusi itu bukan teknologi mahal. Ia ada di tanah, di hutan yang kami lindungi dengan nyawa kami. Agenda iklim harus diwarnai sosiobioekonomi tanpa racun, tanpa eksploitasi,” kata Sonia.
Sonia menyambut baik alokasi 20% dana Tropical Forest Forever Facility (TFFF) untuk Masyarakat Adat. Namun aktivis Indonesia menegaskan bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dalam regulasi perlindungan hak adat.
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi mengatakan, negosiasi yang terjadi di COP30 masih menafikan, meninggalkan dan meminggirkan peran Masyarakat Adat dalam mengatasi krisis iklim.
“Mereka terus mengacuhkan bukti terbaik dari ilmu pengetahuan modern yang menyatakan Masyarakat Adat adalah garda terdepan dalam mengatasi krisis iklim,” kata Rukka yang ikut dalam aksi tersebut. Selain itu, Rukka Sombolinggi juga menagih komitmen pemerintah Indonesia agar Segera sahkan RUU Masyarakat Adat, hentikan perampasan wilayah adat, dan realisasikan 1,4 juta hektare hutan adat yang sudah dijanjikan sejak 2019.”
“Jawaban krisis iklim bukan hanya Masyarakat Adat tetapi Masyarakat Adat dan kalian semua. Jawabannya adalah kita, Kata Rukka menutup orasinya dengan seruan global.