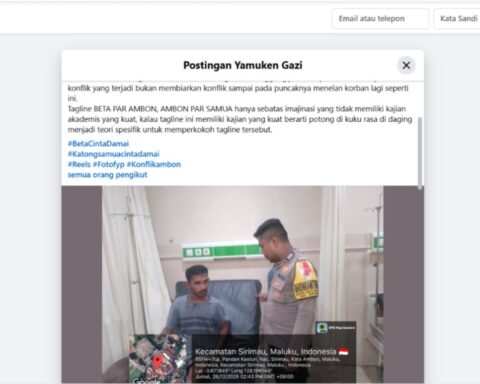Oleh: Adii Tiborius
Hari Ayah Nasional yang diperingati setiap 12 November merupakan momentum reflektif untuk mengakui dan meneguhkan kembali peran strategis seorang ayah dalam ekologi sosial, moral, dan spiritual bangsa Indonesia. Dalam konteks masyarakat yang tengah mengalami disrupsi moral dan percepatan digital, figur ayah menghadapi tantangan eksistensial: antara kehadiran dan kehilangan makna, antara fungsi biologis dan peran ideologis.
Refleksi ini bertujuan meninjau kembali konsep “ayah” secara teoritis, kritis, dan kontekstual — sebagai subjek moral, aktor kultural, dan fondasi etika sosial. Dengan pendekatan multidisipliner (filsafat, sosiologi, teologi, dan psikologi keluarga), tulisan ini mengajak kita melihat ayah bukan hanya dalam dimensi personal, tetapi juga dalam horizon sosial yang lebih luas: ayah sebagai arsitek moral peradaban.
- Makna Historis dan Kultural Hari Ayah Nasional
Hari Ayah Nasional lahir dari kesadaran sosial untuk menempatkan peran ayah sejajar dengan Hari Ibu (22 Desember). Ia menandai pergeseran kesadaran publik bahwa keluarga bukan hanya domain ibu, melainkan ruang kolaborasi antara dua figur simbolik: Ibu sebagai sumber kasih dan Ayah sebagai sumber nilai.
Dalam tradisi Nusantara, peran ayah sering dimaknai dalam spektrum kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Dalam budaya Papua dikenal konsep “Emaawa Owaada” — kerja bersama berbasis kasih dan tanggung jawab; di Jawa dikenal pepatah bapak sabar, anak lancar; di Minahasa, ayah disebut tatahan, penopang. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, sosok ayah bukan hanya biologis, tetapi simbol etis dan moralitas sosial.
- Ayah dalam Perspektif Filsafat Moral
Dalam kerangka filsafat moral, ayah dapat dipahami sebagai subjek praksis etis — individu yang memediasi nilai dan tindakan. Menurut Aristoteles, moralitas lahir dari habitus, yakni kebiasaan bertindak berdasarkan kebajikan (virtue). Ayah menjadi figur pembentuk habitus moral dalam rumah tangga.
Dalam perspektif Kantian, ayah bertindak bukan karena paksaan eksternal, tetapi berdasarkan imperatif kategoris — kesadaran akan kewajiban moral. Sedangkan dalam pemikiran Emmanuel Levinas, wajah ayah adalah wajah tanggung jawab: ia memikul “yang lain” (anak, keluarga, masyarakat) dengan kesadaran etis mendalam.
Dengan demikian, ayah bukan hanya agen ekonomi, tetapi agen moralitas, tempat di mana nilai-nilai kebaikan menemukan bentuk nyata dalam tindakan sehari-hari.
- Ayah sebagai Arsitek Moral
Konsep “arsitek moral” menggambarkan ayah sebagai perancang nilai-nilai kehidupan keluarga. Ia merancang dengan keteladanan, bukan dengan otoritas kaku. Dalam psikologi moral Lawrence Kohlberg, perkembangan moral anak terjadi melalui tahapan imitasi nilai. Artinya, keteladanan ayah lebih kuat daripada instruksi verbal.
Ayah yang jujur menanamkan kejujuran; ayah yang adil menumbuhkan rasa keadilan. Ia menciptakan “arsitektur batin” di mana setiap nilai memiliki ruang dan fungsi. Rumah tanpa arsitek mungkin berdiri, tetapi rapuh; demikian pula keluarga tanpa arah moral akan kehilangan kompas nilai.
- Ayah dan Habitus Etis
Pierre Bourdieu menggunakan istilah habitus untuk menjelaskan bagaimana struktur sosial tertanam dalam tubuh manusia sebagai kebiasaan yang membentuk tindakan. Dalam konteks keluarga, habitus etis ayah adalah pola hidup moral yang secara berulang menciptakan kebajikan kolektif.
Ayah yang disiplin, pekerja keras, dan berdoa secara konsisten menciptakan lingkungan moral yang menular. Habitus etis inilah yang menanamkan cultural capital pada anak: nilai tanggung jawab, resiliensi, dan kepedulian sosial.
Keluarga, dalam hal ini, menjadi “laboratorium moral”, dan ayah berperan sebagai “peneliti utama” yang memastikan nilai diinternalisasi melalui praksis.
- Ayah dan Krisis Maskulinitas di Era Modern
Era 2025 menghadirkan krisis baru dalam identitas ayah: krisis maskulinitas. Model ayah tradisional yang keras, dominan, dan otoriter kini dikritik sebagai toksik, namun model ayah modern yang terlalu permisif juga menimbulkan kebingungan nilai.
Anthony Giddens (1991) menyebut fenomena ini sebagai disembedding — keterlepasannya peran tradisional dari konteks sosialnya.
Ayah hari ini dituntut menemukan model maskulinitas baru: bukan kekuasaan, tetapi pelayanan; bukan dominasi, tetapi dialog; bukan kontrol, tetapi pendampingan.
Di sini ayah menjadi “maskulin humanis”: kuat dalam tanggung jawab, lembut dalam kasih.
- Ayah dan Tantangan Digitalitas
Dalam dunia digital, anak-anak hidup di ruang maya yang tak terbatas. Jika ayah absen, maka algoritma menjadi pendidik baru.
Tantangan abad digital adalah kehadiran yang terputus: ayah di rumah secara fisik, tetapi mentalnya terserap oleh layar.
Maka, peran ayah perlu dimaknai ulang sebagai mentor digital — sosok yang mampu membimbing penggunaan teknologi dengan nilai etis.
Ia tidak menolak teknologi, tetapi menanamkan digital ethics: kejujuran dalam media sosial, tanggung jawab dalam informasi, dan empati dalam interaksi daring.
- Dimensi Teologis: Ayah sebagai Imago Dei
Dalam teologi Kristen, ayah mencerminkan citra Allah sebagai Pater Noster (Bapa Kita). Allah digambarkan bukan sekadar penguasa, melainkan kasih yang melindungi dan membimbing.
Ketika ayah mencintai, mengampuni, dan membimbing dengan sabar, ia menampakkan wajah Allah dalam keluarga.
Teologi keluarga menegaskan bahwa ayah bukan “otoritas sakral” tetapi sakramentalitas kasih: kehadiran nyata dari nilai-nilai ilahi dalam kehidupan sehari-hari.
- Ayah dan Pendidikan Karakter Anak
Pendidikan karakter bukan proyek sekolah, tetapi proyek keluarga. Menurut Thomas Lickona, nilai moral diajarkan melalui knowing, feeling, and doing. Dalam tiga tahap ini, ayah berperan sentral:
- Ia mengajarkan nilai (knowing) melalui nasihat dan kisah hidup,
- Ia menumbuhkan perasaan moral (feeling) melalui kehangatan,
3.Ia menunjukkan tindakan moral (doing) melalui teladan konkret.
Anak yang melihat ayahnya membaca, bekerja jujur, dan menghargai orang lain akan memiliki “kode moral internal” yang kuat.
- Ayah dan Ketimpangan Sosial
Refleksi Hari Ayah juga harus menyinggung realitas sosial: banyak ayah di Indonesia hidup dalam tekanan ekonomi, konflik pekerjaan, bahkan kehilangan makna diri akibat kemiskinan struktural.
Dalam konteks ini, kebijakan sosial seharusnya memberi perhatian pada ketahanan ayah (father resilience).
Keluarga miskin yang kehilangan figur ayah produktif berisiko kehilangan fondasi moral sekaligus ekonomi.
Maka, pembangunan sosial tidak boleh netral gender: ia harus sensitif terhadap kerentanan laki-laki sebagai ayah.
- Ayah dan Spiritualitas Kerja
Kerja bagi ayah bukan hanya ekonomi, tetapi spiritualitas. Dalam teologi kerja (teologi tubuh Yohanes Paulus II), kerja adalah partisipasi dalam karya penciptaan Allah.
Ayah yang bekerja dengan cinta menanamkan etos spiritual kepada anak-anaknya.
Kerja bukan sekadar mencari nafkah, tetapi liturgi kehidupan — persembahan kasih untuk keluarga dan sesama.
- Ayah sebagai Simbol Harapan Sosial
Ketika figur publik kehilangan kejujuran dan pemimpin sosial gagal menjadi teladan, masyarakat mencari panutan baru — dan ayah adalah harapan terakhir.
Ayah yang setia, sederhana, dan bertanggung jawab adalah simbol keutuhan moral bangsa.
Dalam keluarga, ayah menjadi guru nilai; dalam masyarakat, ia menjadi ikon integritas.
Bangsa yang kehilangan ayah yang berkarakter akan kehilangan orientasi moral kolektif.
- Ayah dalam Perspektif Psikologi Eksistensial
Dari perspektif Viktor Frankl, manusia mencari makna bahkan dalam penderitaan. Banyak ayah berjuang dalam diam, menanggung tekanan hidup tanpa ekspresi.
Namun justru dalam penderitaan itu, terbentuk logos — makna eksistensial.
Ayah menemukan makna hidupnya dalam cinta yang ia berikan, bukan dalam tepuk tangan yang ia terima.
Ketenangan seorang ayah sejati terletak pada kesadaran: “Aku berguna, meski tidak selalu terlihat.”
- Ayah dan Keadilan Gender
Perdebatan kesetaraan gender sering meminggirkan ayah, seolah ia simbol patriarki. Namun, kesetaraan sejati bukan menggantikan, melainkan melengkapi peran.
Ayah yang sadar gender bukan kehilangan maskulinitas, tetapi mengubahnya menjadi tanggung jawab relasional.
Ia menghargai ibu sebagai rekan sejajar dalam pengasuhan, bukan bawahan dalam struktur patriarki.
- Krisis Keintiman dan Kehadiran Ayah
Fenomena fatherless generation meningkat akibat perceraian, migrasi kerja, dan disorientasi nilai.
Psikolog John Bowlby menegaskan pentingnya attachment (kelekatan emosional) antara anak dan ayah.
Anak yang kehilangan kelekatan ini cenderung mengalami gangguan identitas moral dan afektif.
Kehadiran ayah yang penuh kasih bukan hanya melindungi secara fisik, tetapi meneguhkan eksistensi emosional anak.
- Ayah dan Pembangunan Sosial
Dalam konteks pembangunan nasional, ayah adalah aktor sosial mikro yang menopang struktur makro bangsa.
Kebijakan keluarga yang memperkuat peran ayah (parental leave untuk ayah, dukungan ekonomi keluarga muda, edukasi ayah digital) adalah investasi sosial jangka panjang.
Bangsa yang membangun ayah sejatinya sedang membangun generasi masa depan.
- Ayah dan Kebijaksanaan Lokal
Nilai-nilai lokal Indonesia mengandung etika paternal yang kuat.
Dalam falsafah Papua: Dou Gai Ekowai (kita hidup bersama dalam kasih), ayah menjadi pengikat harmoni sosial.
Dalam nilai Gotong Royong, ayah adalah penopang kebersamaan.
Kearifan lokal ini memperkaya pemaknaan ayah bukan hanya individual, tetapi komunal dan spiritual.
- Ayah dalam Konteks Gereja dan Pastoral Keluarga
Dalam pastoral keluarga Katolik dan Kristen, ayah dipandang sebagai “imam domestik” — pemimpin rohani rumah tangga.
Ia bukan hanya pengajar iman, tetapi saksi iman melalui tindakan.
Kehadirannya dalam doa bersama, partisipasi pelayanan, dan kehidupan gerejawi memperkuat spiritualitas keluarga.
- Ayah, Narasi, dan Memori
Setiap ayah menulis sejarah kecil dalam kehidupan anaknya.
Kisah perjuangan, pengorbanan, dan ketulusan ayah menjadi memori kolektif moral yang membentuk generasi.
Dalam teori Paul Ricoeur, identitas terbentuk melalui narasi. Maka, ayah adalah penulis pertama narasi moral anaknya.
- Refleksi Kritis: Menjadi Ayah di Tengah Krisis Moral Global
Tantangan terbesar bagi ayah abad ke-21 adalah bertahan sebagai manusia yang berakar dalam nilai.
Ketika dunia memuja efisiensi dan melupakan empati, ayah dipanggil menjadi saksi kemanusiaan.
Ia harus mampu menolak arus konsumerisme, egoisme, dan narsisisme digital, serta meneguhkan nilai kejujuran, kesetiaan, dan pelayanan.
- Epilog: Membangun Peradaban dari Rumah
Ayah adalah fondasi rumah, rumah adalah fondasi bangsa.
Refleksi Hari Ayah Nasional 2025 mengingatkan bahwa pembangunan moral bangsa dimulai dari meja makan keluarga, bukan dari podium politik.
Di sanalah ayah menanamkan nilai, mencipta cinta, dan menjaga masa depan.
Ayah sejati tidak perlu disanjung, cukup diingat bahwa dari keheningannya, lahir generasi yang berani mencintai kebenaran.***
Referensi:
- Aristoteles, Nicomachean Ethics.
- Kant, Immanuel. Groundwork of the Metaphysics of Morals.
- Levinas, Emmanuel. Totality and Infinity.
- Bourdieu, Pierre. Outline of a Theory of Practice.
- Lickona, Thomas. Educating for Character.
- Giddens, Anthony. Modernity and Self-Identity.
- Frankl, Viktor. Man’s Search for Meaning.