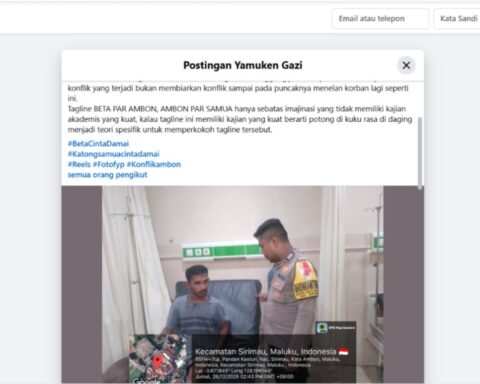Jakarta, — Dalam perhelatan Konferensi Iklim PBB ke-30 (COP 30) di Belem, Brasil, Indonesia menampilkan wajah penuh percaya diri. Mewakili Presiden, Ketua Delegasi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan pidato optimistik: Indonesia disebut siap memperkuat target iklim nasional, menurunkan deforestasi, memperluas energi terbarukan, dan mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.
Bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Hashim meresmikan Paviliun Indonesia, yang mengusung tema “Accelerating Substantial Actions of Net Zero Achievement through Indonesia High Integrity Carbon.” Di dalamnya, tersusun lebih dari 50 sesi diskusi, sebagian besar diisi oleh pejabat tinggi dan pimpinan korporasi.
Paviliun ini bukan sekadar ruang diplomasi, tapi juga pasar. Untuk pertama kalinya, Indonesia membuka forum seller meet buyer — ruang transaksi karbon dengan potensi ekonomi USD 7,7 miliar per tahun dan 90 juta ton unit karbon yang diklaim “berintegritas tinggi.”
Namun, di balik gemerlap itu, suara rakyat di garis depan krisis iklim justru tenggelam.

“COP 30 Jadi Transaksi, Bukan Transformasi”
Direktur Eksekutif WALHI Papua, Maikel Peuki, menilai misi delegasi Indonesia di COP 30 sangat jauh dari semangat keadilan iklim.
“Fokus delegasi pada perdagangan karbon menjadikan misi Indonesia di COP 30 sangat transaksional. Pemerintah mendorong solusi pro-korporasi, seperti co-firing batubara, yang justru menambah beban ekologis,” kata Maikel dalam dialog publik “Suara Rakyat Indonesia untuk COP-30” yang diselenggarakan Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI), 11 November 2025.
Maikel menegaskan, komitmen yang dibanggakan pemerintah berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Dalam setengah abad terakhir, Indonesia kehilangan hampir 40 persen tutupan hutan—dari 162 juta hektare kini hanya tersisa 98 juta hektare.
Antara 2000–2012, hutan primer seluas 6 juta hektare hilang, dan pada 2024 deforestasi alami meningkat lagi menjadi 261.575 hektare. Lebih dari setengah emisi nasional masih berasal dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Ironisnya, pemerintah justru menetapkan target deforestasi “terencana” seluas 10,47 juta hektare untuk dekade 2021–2030.
“Di Papua saja, sekitar 1,3 juta hektare hutan hilang akibat sawit dan tambang. PSN Merauke telah menghancurkan hampir 10 ribu hektare hutan primer hanya dalam dua tahun terakhir,” ujar Maikel.

Diplomasi Hijau yang Tak Sejalan dengan Realita
Selama dua pekan COP 30 berlangsung, Paviliun Indonesia diklaim sebagai etalase “aksi iklim lintas sektor”: kehutanan, energi, industri, hingga limbah. Menteri Hanif menyebut paviliun itu sebagai jembatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas global.
Namun, bagi banyak organisasi lingkungan, diplomasi hijau itu lebih mirip panggung promosi ekonomi karbon.
Skema perdagangan karbon, kata mereka, tidak otomatis menurunkan emisi — hanya memindahkan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lain. “Yang punya uang bisa terus mencemari, asalkan membeli kredit karbon dari wilayah miskin,” ujar Maikel.
Di Bangka Belitung, Ahmad Subhan Hafidz, Direktur WALHI Babel, menggambarkan bagaimana logika ekonomi ekstraktif menelan ruang hidup. Dalam enam tahun (2014–2020), daratan seluas 460 ribu hektare hutan tropis hilang. Dari total 1,6 juta hektare daratan, 70 persen sudah dibebani izin tambang dan sawit.
“Terdapat 12.607 lubang tambang yang tidak direklamasi. Akibatnya, muncul bencana ekologis beruntun — banjir besar 2016, kekeringan 2015, abrasi 42 ribu hektare garis pantai, dan 26 korban tenggelam di kolong tambang, sebagian besar anak-anak,” ujarnya.
Ketika yang Rentan Tak Dihitung
Dari Sulawesi Selatan, Maria Un, perempuan disabilitas sekaligus anggota komunitas adat, menyoroti sisi lain dari ketimpangan iklim: diskriminasi dalam bencana.
“Penyandang disabilitas paling sulit selamat saat banjir atau longsor. Tempat penampungan tidak aksesibel dan informasi bencana sulit diakses. Bantuan pun tak mempertimbangkan kebutuhan spesifik kami,” katanya.
Sementara di pesisir utara Maluku, Gofur Kaboli, nelayan kecil asal Ternate, mengingatkan bahwa kebijakan iklim yang tak menjamin perlindungan bagi nelayan sama saja meniadakan masa depan mereka.
“Nelayan adalah tulang punggung negeri, tapi paling terdampak perubahan iklim. Keputusan di COP 30 harus memberi jaminan bagi kami menghadapi cuaca ekstrem,” ujarnya.
Seruan: Transisi Berkeadilan, Bukan Transaksi Karbon
Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam JustCOP (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim)menegaskan bahwa transisi energi Indonesia hanya bisa disebut “berkeadilan” jika menempatkan masyarakat adat, nelayan, petani, dan penyandang disabilitas sebagai aktor utama perubahan.
Mereka mendesak agar agenda adaptasi iklim berbasis hak, dengan indikator perlindungan kelompok rentan, pengetahuan lokal, dan hak tenurial atas ruang hidup. Pendanaan iklim harus langsung ke komunitas, bukan hanya ke lembaga besar atau bank multilateral.
“Transisi berkeadilan bukan sekadar ganti sumber energi, tapi tentang siapa yang ikut dalam perubahan dan siapa yang ditinggalkan,” ujar Maikel Peuki menutup pernyataannya.