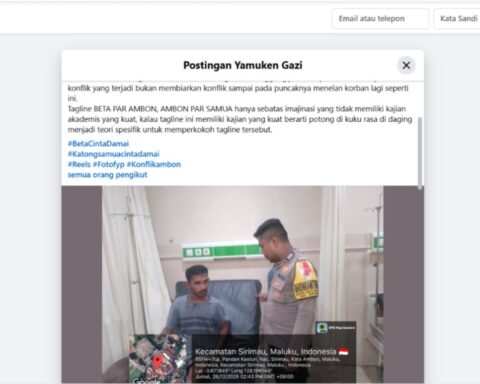Jakarta, — Dua organisasi masyarakat sipil, Amnesty International Indonesia (AII) dan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), menolak keputusan pemerintah Prabowo–Gibran yang memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan Sarwo Edhie Wibowo.
Menurut keduanya, langkah itu adalah bentuk pemutaran balik sejarah, pengkhianatan terhadap cita-cita Reformasi 1998, dan penghinaan terhadap jutaan korban pelanggaran HAM berat selama tiga dekade rezim Orde Baru.
“Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, bukan justru memuliakan pelaku pelanggarannya,” ujar Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, dalam pernyataannya, Senin, 10 November 2025.
Usman menegaskan, kesalahan rezim Soeharto bukanlah sekadar “pelanggaran administratif” atau “kesalahan politik”, melainkan kejahatan berat terhadap kemanusiaan (most serious crimes).

Ia menyebut bahwa langkah pemberian gelar pahlawan ini justru menormalisasi impunitas dan menghapus batas moral bangsa.
“Filsafat kebudayaan tanpa norma dasar moralitas universal akan meniadakan kemampuan bangsa membedakan benar dan salah. Itu arah menuju malapetaka,” katanya.
Deretan Pelanggaran HAM Berat di Era Orde Baru
Selama 32 tahun berkuasa (1966–1998), Soeharto dan aparatus militernya bertanggung jawab atas berbagai kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat di berbagai daerah Indonesia.
AII dan AKSI mencatat setidaknya delapan peristiwa besar yang menjadi bukti kelam rezim tersebut:
1. Pembantaian massal 1965–1966 terhadap orang-orang yang dituduh anggota atau simpatisan PKI.
Lebih dari 500 ribu orang dibunuh, dan ratusan ribu lainnya dipenjara tanpa pengadilan.
2. Penembakan misterius (Petrus) 1982–1985, operasi militer terselubung yang menewaskan ribuan orang muda dengan tuduhan kriminal.
3. Tragedi Tanjung Priok (1984) dan Talangsari (1989), pembantaian terhadap warga sipil dan jamaah yang menentang rezim otoriter.
4. Kekerasan sistematis di Aceh, Timor Timur, dan Papua, termasuk penyiksaan, penghilangan paksa, dan pembunuhan di luar hukum.
5. Penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1997–1998, menjelang kejatuhan Soeharto.
6. Militerisasi kehidupan politik dan ekonomi, yang menciptakan ketakutan kolektif dan membungkam kebebasan pers.
7. KKN yang dilembagakan secara sistemik, memperkaya kroni dan keluarga melalui perusahaan-perusahaan raksasa yang terafiliasi dengan kekuasaan.
8. Kontrol ketat terhadap sejarah dan pendidikan, yang memanipulasi ingatan publik tentang kekerasan negara.
“Rezim Soeharto memproduksi trauma kolektif bagi bangsa Indonesia. Ia tidak layak dipanggil pahlawan,” tegas Marzuki Darusman, Ketua AKSI sekaligus mantan Jaksa Agung RI.
Pemutaran Sejarah dan Pengkhianatan Reformasi
Kedua organisasi menilai, pemberian gelar ini merupakan bagian dari proyek politik besar untuk menulis ulang sejarah Indonesia.
Mereka menyoroti peran Menteri Kebudayaan yang ikut mengusulkan nama Soeharto, sementara di saat yang sama memimpin proyek penulisan ulang Sejarah Nasional Indonesia.
Langkah itu dinilai berpotensi menghapus kisah korban dan perlawanan rakyat terhadap otoritarianisme.
“Kita sedang menyaksikan bagaimana negara mencoba menghapus luka sejarah dengan cara memberi medali kepada pelaku,” ujar Usman.
Pemberian gelar itu juga dinilai melengkapi pola kemunduran demokrasi dan penguburan cita-cita Reformasi.
Mulai dari rencana mencabut nama Soeharto dari TAP MPR XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara bersih dari KKN, hingga usulan Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan yang kini diadopsi pemerintah.
“Semua ini membentuk ekosistem impunitas yang sempurna,” kata Marzuki.
“Negara yang seharusnya berpihak pada korban, kini justru memuliakan pelaku.”
Desakan Pembatalan Gelar
AII dan AKSI mendesak pemerintah untuk segera membatalkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan Sarwo Edhie Wibowo.
Mereka menyebut keputusan itu tidak hanya menyakiti keluarga korban, tetapi juga mengkhianati memori publik dan arah bangsa.
Kedua lembaga menyerukan agar negara kembali berpihak kepada korban, menegakkan hukum, dan membuka seluruh arsip pelanggaran HAM masa lalu.
“Kalau bangsa ini masih punya nurani, maka tempat Soeharto bukan di tugu pahlawan, tapi di pengadilan sejarah,” pungkas Usman Hamid.