PADA hari Jum’at, tanggal 23 Pebruari 2024, jam: 12.10 pm – 12.40 pm, 2 (dua) bulan yang lalu, Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri (MENLU) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berpidato untuk dan atas nama serta mewakili pemerintah NKRI di ‘Mahkamah Internasional’ (International Court of Justice/Cour Internationale de Justice), Istana Perdamaian (Peace Palace/Palais de la Paix/Vredespaleis), Carnegieplein 2, 2517 KJ The Hague (Den Haag), Netherlands (Belanda).
Retno Marsudi merupakan salah seorang dari 52 (lima puluh dua) orang yang juga berpidato untuk dan atas nama serta mewakili pemerintah Negara mereka masing-masing, dan 3 (tiga) orang lainnya yang masing-masing dari mereka berpidato untuk dan atas nama serta mewakili pengurus 3 (tiga) organisasi internasional (international organization) yaitu, Uni Afrika (African Union), Organisasi Kerjasama Negara-negara Islam (OKI) (Organization of Islamic Cooperation (OIC)), dan Liga Negara-negara Arab (League of Arab States).
Kegiatan dalam bentuk “rapat dengar pendapat (public hearings)” sebagaimana tersebut di atas, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Internasional selama 6 (enam) hari ini, yaitu dari hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2024 hingga hari Senin, tanggal 26 Pebruari 2024, dengan topik, Akibat Hukum yang muncul dari Kebijakan Israel di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Jerusalem Timur (Legal Consequences arising from the Policies of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem), adalah berdasarkan “permintaan pendapat Mahkamah Internasional (Request for Advisory Opinion)” oleh ‘Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)’ (General Assembly of the United Nations) pada bulan Desember tahun 2022 lalu.
Akan tetapi, sejak Retno Marsudi mengawali pidatonya di dalam gedung Mahkamah Internasional hingga selesai, selama itu pula berlangsung juga demonstrasi di luar gedung Mahkamah Internasional. Demonstran yang terdiri dari para aktivis dan simpatisan serta pendukung ‘Gerakan Acheh Merdeka’ (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan Republik Maluku Selatan (RMS) dalam orasinya menyerukan agar Retno Marsudi dan pemerintah NKRI: “KACA DIRI (CERMIN DIRI)”.
Disamping itu, beredar pula “Surat Terbuka dari Rakyat Maluku kepada Mahkamah Internasional (English: Open Letter from The People of Maluku to The International Court – TitaStory)” pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2024, sehari sebelum Retno Marsudi berpidato di gedung Mahkamah Internasional, tepatnya pada hari Jum’at, tanggal 23 Pebruari 2024. Surat Terbuka ini, berisikan “pesan khusus (special message)” kepada Mahkamah Internasional bahwa, apa yang akan diucapkan oleh Retno Marsudi dalam pidatonya pada hari Jum’at, tanggal 23 Pebruari 2024 nanti, adalah seperti kata orang bijak: “Memercik air basah wajah sendiri” dan/atau “Ketika 1 (satu) jari menunjuk kesalahan orang lain, 4 (empat) jari sedang menunjuk kesalahan diri sendiri”. … “ke-empat jari itu”, adalah: “Maluku, Papua, Acheh, dan kasus-kasus pelanggaran HAM (berat) lainnya”.
Ironi Pidato Retno Marsudi
Pada hari ini, Kamis, tanggal 25 April 2024, tepatnya 74 (tujuh puluh empat) tahun lalu, pada hari dan tahun yang berbeda, tetapi pada tanggal, dan bulan yang sama, yaitu pada hari Selasa, tanggal 25, bulan April, tahun 1950, “penduduk/rakyat/bangsa (people)” dalam “wilayah/petuanan/teritori (territory)” kepulauan Maluku bagian Selatan memproklamasikan berdirinya suatu negara yang berdaulat dan merdeka dengan nama: “REPUBLIK MALUKU SELATAN (RMS)”.
Proklamasi dimaksud di atas, adalah sebagaimana yang tersebut berikut ini: “Memenuhi kemauan yang sungguh, tuntutan dan desakan rakyat Maluku Selatan, maka dengan ini kami proklamir KEMERDEKAAN MALUKU SELATAN, de facto de jure, yang berbentuk Republik, lepas dari pada segala perhubungan ketatanegaraan Negara Indonesia Timur dan R.I.S., beralasan N.I.T. sudah tidak sanggup mempertahankan kedudukan sebagai Negara Bahagian selaras dengan peraturan-peraturan Muktamar Denpasar yang masih syah berlaku, juga sesuai dengan keputusan Dewan Maluku Selatan tertanggal 11 Maret 1947, sedang R.I.S. sudah bertindak bertentangan dengan keputusan-keputusan K.M.B. dan Undang-Undang Dasarnya sendiri”.

Proklamasi tersebut di atas, membuktikan dengan sendirinya bahwa pembentukkan RMS sebagai suatu Negara yang berdaulat dan merdeka telah memenuhi unsur politis yaitu, “Kehendak Rakyat dalam Wilayah Maluku Selatan”, dan unsur yuridis yaitu, “Republik Indonesia Serikat (RIS) telah melanggar Keputusan-keputusan ‘Komperensi Meja Bundar’ (KMB) dan Konstitusinya sendiri”. Pemenuhan kedua unsur tersebut telah menjadi ‘Alas Hak dan/atau Titel’ (Title) yang sah untuk berdirinya RMS sebagai suatu Negara yang berdaulat dan merdeka secara legal berdasarkan hukum (internasional).
Dalam hukum internasional, “kehendak rakyat” telah termanifestasikan dalam prinsip “Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri (the Right of Self-determination)” yang mekanisme implementasinya dan/atau cara pelaksanaannya dilakukan melalui apa yang dinamakan sebagai: “Plebisit (Plebiscite)”. Karen Parker, J. D., menyatakan dalam halaman 7 dari “briefing paper” yang dipresentasikan pada sidang Komisi ‘Hak-hak Asasi Manusia’ (HAM) PBB di Jenewa, Austria, pada bulan Maret tahun 1996, di bawah judul, Republik Maluku: The Case for Self-determination, bahwa: “Adalah sangat jelas bahwa dalam perjanjian-perjanjian pada ‘Konperensi Meja Bundar (KMB)’ (Round Table Conference (RTC) / Rondetafelconferentie (RTC) – Penulis), Rakyat Maluku diberi hak Prerogative untuk menolak penggabungan kedalam RIS, baik dengan cara pemungutan suara negative dalam suatu plebisit pra-gabung atau dengan menolak untuk menyetujui ‘Undang-Undang Dasar Sementara’ (UUDS)”.
Karen Parker, J. D., selanjutnya menyatakan dalam halaman 11 dari “briefing paper” dibawah judul yang sama sebagaimana tersebut di atas, bahwa: “Perjanjian-perjanjian yang dihasilkan dalam KMB/RTC dan perjanjian-perjanjian bilateral sebelumnya (antara lain: Perjanjian Linggardjati, hari Selasa, tanggal 25 Maret 1947, dan Perjanjian Renville, hari Sabtu, tanggal 17 Januari 1948 – Penulis) secara jelas memberi hak kepada rakyat Maluku untuk menentukan nasibnya sendiri. Meskipun tidak ada suatu pengakuan yang dapat dijadikan pegangan dalam perihal hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Maluku, rakyat Maluku memenuhi segala persyaratan dan/atau pengujian Hukum Internasional dalam perihal Hak untuk menentukan nasib sendiri. … Tuntutan rakyat Maluku akan hak untuk menentukan nasib sendiri – sekalipun dengan tidak adanya suatu perjanjian yang khusus – adalah sangat kuat”.
Pernyataan Karen Parker seperti tersebut di atas, adalah sejalan dengan keputusan Pengadilan Banding Amsterdam, “Perseroan Terbatas (PT) (Naamloose Vennotschap (NV))” Koninklijke Paketvaart Maatschappij melawan Repoebliek Maloekoe Selatan, hari Kamis, tanggal 8 Pebruari 1951, Yurisprudensi Belanda 1950, nomor: 804, halaman 1424 (Gerechtshof Amsterdam, N. V. Koninklijke Paketvaart Maatschappij vs Repoebliek Maloekoe Selatan, 8 Pebruari 1951, Nederlandse Yurisprudentie 1950, no. 804, p. 1424) sebagaimana yang dikutip oleh N. J. C. M. Kappeyne van de Cappello, LL.D., dalam tulisan di bawah judul, Relation to the United Nations, yang diterbitkan di Belanda pada tahun 1960 oleh A. W. Sythoff – Leyden, bahwa: “Proklamasi kemerdekaan RMS sebagai suatu Negara yang berdaulat harus dipertimbangkan sebagai suatu metode implementasi hak untuk menentukan nasib sendiri oleh dan/atau atas/nama Rakyat Maluku Selatan, karena perihal tersebut telah disetujui oleh Rakyat Maluku Selatan”.
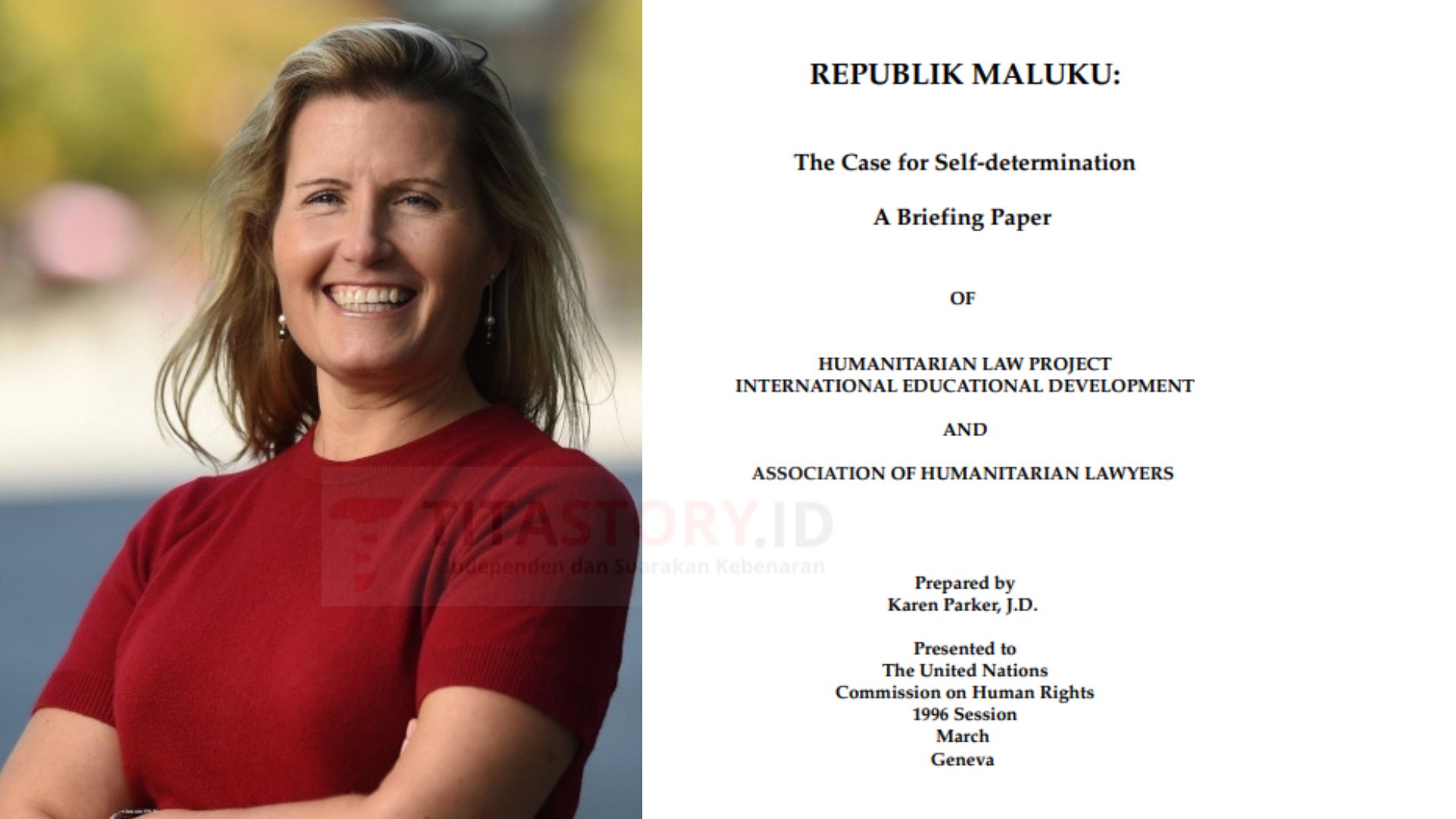
(Catatan: Karen Parker, J. D., adalah seorang Direktur pada ‘Proyek Hukum Kemanusiaan’ (Humanitarian Law Project (HLP)) dan/atau Pembangunan Pendidikan Internasional (International Educational Development (IED)), dan merupakan seorang Pengacara Hukum pada ‘Asosiasi Pengacara-pengacara Kemanusiaan’ (Association of Humanitarian Lawyers (AHL)) yang mengkhususkan diri dalam masalah HAM (Human Right’s) dan ‘Hukum Kemanusiaan’ (Humanitarian Law) dimana Karen Parker merupakan Wakil Utama organisasi HLP/IED di PBB, di Jenewa, Austria, dan di New York, Amerika Serikat (AS) (the United States of America (USA)). HLP/IED yang berkantor pusat di 8124 West Third Street, Los Angeles, California 90048, USA, merupakan suatu ‘Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)’ (Non-Governmental Organization (NGO)) yang tidak berorientasi pada sekte manapun (non-sectarian) dan yang telah diberi kepercayaan untuk pengadaan jasa konsultasi kepada badan-badan PBB oleh mantan ‘Sekretaris Jenderal’ (Sekjen) PBB, Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjold (1905-1961)).
Sebelumnya, pada tahun 1960, Dr. Gesina Hermina Johanna van der Molen, juga telah menyatakan dalam tulisan di bawah judul, The Legal Position According to International Law, yang diterbitkan di Belanda pada tahun 1960 oleh A. W. Sythoff – Leyden, bahwa: “Mempertimbangkan masalah RMS dari sudut pandang hukum tidak ada kesangsian terhadap keberadaannya sebagai suatu negara dalam pengertian hukum internasional modern. Sekali lagi ingin ditekankan bahwa Negara RMS sudah menggunakan hak untuk menentukan nasib sendiri secara sah menurut hukum. … Dari kenyataan-kenyataan dan/atau fakta-fakta tersebut di atas dan ketentuan-ketentuan yang sah berlaku memperlihatkan bukti bahwa RMS sebagai suatu negara memiliki hak yang sempurna untuk memberlakukan hak untuk menentukan nasib sendiri ‘mereka’ (Rakyat Maluku Selatan dalam Negara Republik Maluku Selatan – Penulis)”.
Gesina H. J. van der Molen, selanjutnya menyatakan dalam tulisan dibawah judul yang sama, bahwa: “Sangat sedikit negara dapat merdeka secara sah menurut hukum, sama halnya dengan Negara RMS ini. Hak hidup rakyat Maluku Selatan dijamin oleh hukum internasional umum yang berlaku secara universal sama baiknya dengan perjanjian formal”. Mengenai keabsahan RMS sebagai suatu negara yang berdaulat dan merdeka berdasarkan hukum (internasiona) sebagaimana yang dinyatakan oleh Gesina H. J. Van der Molen tersebut, Hendrik Jan Roethof, menyatakan dalam tulisan di bawah judul, An Existing State, yang diterbitkan di Belanda pada tahun 1960 oleh A. W. Sythoff – Leyden, bahwa: “Negara RMS memiliki status hukum yang sangat besar melebihi negara-negara lain yang kedaulatannya telah diakui dan telah diterima sebagai anggota PBB”.
Pernyataan H. J. Roethof sebagaimana tersebut di atas, merujuk pada keputusan Pengadilan ‘s-Gravenhage, Republik Maluku Selatan melawan Badan Hukum Nieuw-Guinea, hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 1954, Dutch Case Law 1954, nomor: 549, halaman 1040 (Rechbank ‘s-Gravenhage, Republiek Maluku Selatan vs Rechtspersoon Nieuw-Guinea, 10 Februari 1954, Nederlandse Jurisprudentie 1954, no. 549, p. 1040), bahwa: “Melalui bukti-bukti yang diajukan dan juga sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa RMS adalah suatu negara yang sah, berdaulat, dan merdeka”. Keputusan Pengadilan tersebut mengacu pada pendapat para ahli hukum internasional yang tergabung dalam “Asosiasi Hukum Internasional Cabang Belanda (AHICB) (the Netherlands Association for International Law (NAIL)/de Nederlandse Vereninging voor International Recht (NVIR)) yang dalam sidangnya di Rotterdam, Belanda, pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 1950, menyatakan, bahwa: “Negara RMS telah memiliki hak untuk memproklamasikan kemerdekaannya itu terhadap pendapat siapapun juga”.
Jika merujuk pada keseluruhan uraian penjelasan ilmiah dan/atau akademik sebagaimana tersebut di atas tentang proses pembentukan RMS sebagai suatu negara yang berdaulat dan merdeka berdasarkan ketentuan hukum internasional, maka dapat disimpulkan, bahwa: “RMS tidak membutuhkan ‘pengakuan’ (recognition) dari siapapun juga dan dalam bentuk apapun juga bahkan dengan cara yang bagaimanapun juga”. Dalam hubungan dengan perihal ini, Prof. Huala Adolf, SH., LL.M., Ph.D., dalam halaman 64 dari buku dibawah judul, Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional, yang diterbitkan di Bandung pada tahun 2011 oleh penerbit Keni Media, menyatakan, bahwa: “Bagi negara (pemerintah) baru yang lahir secara ‘sepihak’ (unilateral), tidak sesuai konstitusi (inconstitutional), di luar ketentuan Piagam PBB (violates the rules of the UN Charter) atau ‘revolusi’ (revolution), lembaga ‘pengakuan’ (recognition) karenannya menjadi penting untuk mendapatkan ‘alas hak dan/atau titel’ (title) yang sah atas ‘wilayah dan/atau teritori’ (territory)”.
Sejalan dengan pernyataan Huala Adolf sebagaimana tersebut di atas, Prof. Rebecca M. M. Wallace, MA., LL.B., Ph.D., dalam halaman 103 dari buku dibawah judul, International Law, yang diterbitkan di London, Inggris, pada tahun 1986 oleh penerbit Sweet & Maxwell, menyatakan, bahwa: “Pengakuan (recognition) terhadap ‘alas hak dan/atau titel’ (title) yang sah atas ‘wilayah dan/atau teritori’ (territory) oleh suatu ‘satuan’ (negara) kepada keberadaan ‘negara baru’ (new state) yang terbentuk dengan cara yang ‘tidak sesuai konstitusi’ (inconstitutional), misalnya dengan ‘revolusi’ (revolution) atau melalui ‘pernyataan kemerdekaan secara sepihak’ (unilateral proclamation of independence), akan bergantung pada ‘pengakuan’ (recognition) oleh ‘anggota-anggota’ (negara-negara) masyarakat internasional lainnya, dan ‘alas hak dan/atau titel’ (title) yang sah atas ‘wilayah dan/atau teritori’ (territory) pada akhirnya hanya dapat dikukuhkan bila suatu pengakuan atas kenyataan-kenyataan dan/atau fakta-fakta yang ada dapat diterima”.
Dalam hubungan dengan konsep ‘Pengakuan’ (recognition) sebagaimana tersebut di atas, hukum internasional tidak menganut ‘Doktrin Konstitutif’ (Constitutive Doctrine) tetapi hukum internasional menganut ‘Doktrin Deklaratoir dan/atau Doktrin Evidenter’ (Declaratory Doctrine/Evidentiary Doctrine). Mengenai Doktrin Deklaratoir ini, S. Tasrif, SH., dalam halaman 30 dari buku dibawah judul, Hukum Internasional tentang Pengakuan dalam Teori dan Praktek, yang diterbitkan di Bandung pada tahun 1987 oleh penerbit Abardin, menyatakan, bahwa: “Pengakuan hanyalah bersifat ‘pernyataan dan/atau deklarasi’ (declaration) dari pihak negara-negara lain, bahwa suatu negara baru telah mengambil tempat disamping negara-negara yang telah ada” (Shaw, Malcolm N. (2013) Hukum Internasional. Bandung: Nusa Media, 439). Dalam hukum internasional, Doktrin Deklaratoir ini dapat ditemukan dalam Konvensi Montevideo tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Negara-negara (Montevideo Convention on the Rights and Obligations of States) hari Selasa, tanggal 26 Desember 1933, khususnya Pasal 3, bahwa: “Keberadaan dan/atau eksistensi politik suatu negara adalah bebas dari pengakuan negara-negara lain (The political existence of the State is independent of recognition by the other States)”.
Disamping itu, Doktrin Deklaratoir ini dapat ditemukan juga dalam Pasal 9 dari Piagam Bogota, yaitu Piagam pembentukkan ‘Organisasi Negara-negara Amerika (ONA)’ (Organization of American States (OAS)) pada hari Jum’at, tanggal 30 April 1948. Dr. Sefriani, SH., M.Hum., menyatakan dalam halaman 158 dari buku dibawah judul, Hukum Internasional Suatu Pengantar, yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 2016 oleh penerbit Rajawali Pers, bahwa, Doktrin Deklaratoir tersebut dikuatkan pula oleh beberapa putusan pengadilan, yang salah satu diantara putusan pengadilan itu adalah, putusan Mahkamah Arbitrase dalam kasus Deutcsche Continental Gas – Gesellschaft vs Polish State 1929. Selain itu, Prof. Jawahir Thontowi, SH., Ph.D., dan Pranoto Iskandar, SH., LL.M., menyatakan dalam halaman 133 & 134 dari buku dibawah judul, Hukum Internasional Kontemporer, yang diterbitkan di Bandung pada tahun 2006 oleh penerbit Refika Aditama, bahwa, Doktrin Deklaratoir ini juga dianut oleh ‘Institut Hukum Internasional’ (International Law Institute/Institut de Droit Internationale), dan Doktrin Deklaratoir ini diadopsi pula oleh ‘Komisi Arbitrase Masyarakat Eropa untuk Yugoslavia’ (the European Community Arbitration Commission on Yugoslavia).
Jika merujuk pada keseluruhan uraian penjelasan ilmiah dan/atau akademik sebagaimana tersebut di atas tentang pengakuan dalam hukum internasional, maka dalam hubungan dengan RMS dapat disimpulkan, bahwa: “atas dasar ketentuan Hukum Internasional, khususnya Pasal 3 dari Konvensi Montevideo yang menganut Doktrin Deklaratoir tentang Pengakuan, maka keberadaan RMS sebagai suatu negara yang berdaulat dan merdeka adalah suatu kenyataan yang tidak membutuhkan pengakuan secara resmi / formal / khusus / spesifik dari negara lain. Pengakuan dari negara lain terhadap eksistensi RMS sebagai suatu negara yang berdaulat dan merdeka, semata-mata hanya merupakan tindakan deklarasi biasa yang tidak memiliki implikasi hukum”. Namun demikian, sekalipun pengakuan negara lain itu tidak menjadi ‘syarat’ (condition) untuk keberadaan RMS sebagai suatu negara yang berdaulat dan merdeka, tetapi keberadaan RMS sebagai suatu negara yang berdaulat dan merdeka berdasarkan hukum internasional telah memperoleh “pengakuan” melalui kehadiran RMS sebagai pihak dan/atau subjek dalam sidang pengadilan pada beberapa kasus hukum, baik di Negara Belanda maupun di Nieuw-Guinea.
Bahkan keputusan hakim dalam salah satu kasus hukum dimana RMS hadir sebagai pihak dan/atau subjek didalamnya, yaitu kasus Pengadilan Amsterdam (persidangan singkat/persidangan cepat) Repoebliek Maloekoe Selatan melawan “Perseroan Terbatas (PT) (Naamloose Vennotschap (NV))” Koninklijke Paketvaart Maatschappij, hari Kamis, tanggal 2 November 1950, Yurisprudensi Belanda 1950, nomor: 804, halaman 1424 (Rechbank Amsterdam (Kort Geding) Repoebliek Maloekoe Selatan vs N. V. Koninklijke Paketvaart Maatschappij, 2 November 1950, Nederlandse Jurisprudentie 1950, no. 804, p. 1424) dinyatakan, bahwa: “Pengakuan terhadap RMS sebagai suatu Negara yang berdaulat dan merdeka – yang keberadaannya memang sudah merupakan suatu kenyataan – oleh pemerintah Negara Kerajaan Belanda telah dimuat dalam keputusan Parlemen Negara Kerajaan Belanda pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 1949, Lembaran Negara J 570 (Keputusan Penyerahan Kedaulatan Kepada RIS) dengan mana perjanjian ketiga tentang Langkah-langkah ‘Peralihan dan/atau Transisi’ (Transitional Measures) sebagai salah satu hasil dari KMB telah disetujui dan menjadi bagian dari keputusan ini”.
Selain seluruh uraian penjelasan ilmiah dan/atau akademik mengenai RMS oleh para ahli hukum (internasional) sebagaimana tersebut di atas, adalah Des Alwi Abubakar (1927–2010) seorang sejarawan, diplomat, penulis, dan advokat, yang mengalami sendiri proses pembentukan RMS pada tahun 1950, memberikan kesaksian dalam halaman 337 dari buku dibawah judul, Sejarah Banda Naira, yang diterbitkan di Malang pada tahun 2010, oleh penerbit Pustaka Bayan, bahwa: “Negara yang baru dibentuk ini (RMS – Penulis) sejak lahir sudah memiliki kelembagaan negara seperti Presiden, Kabinet, Parlemen, dan lembaga-lembaga penting lainnya. Paling penting yang perlu dicatat bahwa Republik yang baru ini (RMS – Penulis) sudah memiliki Angkatan Bersenjatanya”. Prof. Dr. Dieter Bartels, menyatakan dalam halaman 686 dari buku dibawah judul, Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim-Kristen Hidup Berdampingan Di Maluku Tengah, jilid II tentang Sejarah, yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 2017 oleh penerbit ‘Kepustakaan Populer Gramedia’ (KPG), bahwa: “Angkatan Bersenjata RMS hanya berjumlah sekitar kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) orang tentara banyaknya, yang terdiri atas pasukan KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger), dan beberapa anggota KST (Korps Speciale Troepen)”.
Dalam hubungan dengan kekuatan Angkatan Bersenjatan RMS sebagaimana tersebut di atas, Johannes Hermanus Manuhuttu, Presiden pertama RMS, memberikan pengakuan di depan sidang pengadilan militer NKRI di Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 1955, sebagaimana yang dikutip oleh, Jusuf Abdullah Puar, dalam halaman 74 dari buku dibawah judul, Peristiwa Republik Maluku Selatan, yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 1956 oleh penerbit Bulan Bintang, bahwa: “Kekuatan ‘Angkatan Perang RMS’ (AP-RMS – Penulis) hanya berjumlah sekitar kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) orang tentara banyaknya”. Sebelumnya, Daantje Jacob Samson, Panglima Besar Tentara dalam kabinet pertama RMS, memberikan pengakuan di depan sidang pengadilan militer NKRI di Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 1955, sebagaimana dikutip juga oleh, J. A. Puar, dalam halaman 173 – 176 dari buku dibawah judul yang sama, bahwa: “Kekuatan RMS pada waktu itu ada 2.000 (dua ribu) orang prajurit dan mempunyai senjata kira-kira 1.200 (seribu dua ratus) pucuk senapan saja. … Persediaan amunisi pada waktu itu hanya dapat dipakai untuk mengadakan pertempuran kira-kira selama 7 (tujuh) hari saja. … Ambon dipertahankan hanya dengan kekuatan tentara kira-kira sebesar 1.000 (seribu) orang prajurit saja”.

Dengan kekuatan AP-RMS sebagaimana tersebut di atas, pemerintah dan rakyat Negara RMS harus berjuang “membela diri (self devense)” dari ‘serbuan/invasi’ (invasion) “Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) (Sekarang: Tentara Nasional Indonesia (TNI))” yang merupakan suatu bentuk perbuatan ‘penyerangan/agresi’ (aggression). Invasi dan agresi ini dilakukan oleh pemerintah NKRI melalui suatu “operasi gabungan (Joint Operation/Combined Operation)” yang pertama dan yang terbesar sejak berdirinya ‘Negara Republik Indonesia’ (NRI) pada hari jum’at, tanggal 17 Agustus 1945. Operasi Militer dengan nama sandi ‘Gerakan Operasi Militer’ (GOM) III ini bertujuan untuk ‘menduduki/mengokupasi’ (occupation) serta ‘mencaplok/menganeksasi’ (annexation) Negara RMS. Pasukan yang mengikuti GOM III ini kemudian dibagi kedalam 3 (tiga) group, yaitu: Group I, dibawah komando Mayor Achmad Wiranatakusumah; Group II, dibawah komando Letnan Kolonel Ignatius Slamet Riyadi; dan Group III, dibawah komando Mayor Suryo Subandrio, dimana GOM III ini kemudian juga dibagi lagi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu: (1) Operasi Malam; (2) Operasi Fajar; (3) Operasi Senopati; (4) Operasi Kepulauan Maluku; (5) Operasi Bintang Siang; dan (6) Operasi Tertutup.
Operasi GOM III sebagaimana tersebut di atas, melibatkan sebanyak hampir kurang lebih 2 (dua) Divisi tentara APRIS dan/atau sejumlah hampir kurang lebih 20 (dua puluh) batalyon pasukan APRIS dan/atau setara dengan sekitar hampir kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) orang prajurit APRIS berikut kompi ‘Kavaleri’ (Tank), Artileri (Meriam), dan Zeni (Konstruksi) yang terdiri dari batalyon-batalyon dari pulau Jawa, seperti: Batalyon Siliwangi dari Jawa Barat, Batalyon Diponegoro dari Jawa Tengah, dan Batalyon Brawijaya dari Jawa Timur; 3 (tiga) unit pesawat terbang pembom ‘Angkatan Udara Republik Indonesia’ (AURI) Bomber B-25, 2 (dua) unit pesawat terbang tempur Mustang, dan 2 (dua) unit pesawat terbang ampibhi PBY Catalina; serta 14 (empat belas) unit kapal perang ‘Angkatan Laut Republik Indonesia’ (ALRI), ditambah dengan 3 (tiga) kapal niaga yang berfungsi sebagai kapal ‘Rumah Sakit’ dan kapal ‘Angkutan Logistik’ (Puar, Jusuf Abdullah (1956) Peristiwa Republik Maluku Selatan. Yogyakarta: Bulan Bintang; Pour, Julius (2008) Ign. Slamet Rijadi dari Mengusir Kempeitai sampai Menumpas RMS. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; Israr, Hikmat (2010) Kolonel A. E. Kawilarang Panglima Pejuang dan Perintis Kopassus. Jakarta: Asmi Publishing; Matanasi, Petrik (2015) Joost. Yogyakarta: Sibuku Media).
Hasil akhir dari Operasi GOM III sebagaimana tersebut di atas, adalah terbunuhnya penduduk sipil dalam wilayah Negara RMS, dan luluh-lantaknya ibukota Negara RMS, yaitu: “Kota Amboina”. Perihal jumlah korban penduduk sipil pada saat itu adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Dieter Bartels (2017: 686): “Korban terbesar adalah dari penduduk sipil, dimana sekitar 5.000 (lima ribu) – 8.000 (delapan ribu) orang kehilangan nyawanya”. Sedangkan perihal kondisi Kota Ambon pada saat itu adalah sebagaimana yang ditulis oleh I. O. Nanulaitta dalam halaman 132-134 dari buku dibawah judul, Mr. Johannes Latuharhary, Hasil Karya dan Pengabdiannya, yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 2009 oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, berdasarkan kesaksian dari Mr. Johannes Latuharhary sendiri: “Alangkah bedanya kota Ambon 11 tahun lalu (1939 – Penulis) dengan kota Ambon yang dilihatnya kini (hari Selasa, tanggal 12 Desember 1950 – Penulis) … puing-puing gedung … bekas-bekas kebakaran … yang masih berdiri penuh dengan lobang-lobang tembusan peluru … tanda betapa hebatnya pertempuran yang terjadi di Kota Ambon … baru pada hari Jum’at, tanggal 3 November 1950 yang lalu, kota Ambon diduduki oleh militer Indonesia. 90% dari kota Ambon telah rata dengan tanah”.
Hebatnya pertempuran antara APRIS (TNI) versus AP-RMS seperti disaksikan sendiri oleh Mr. Johannes Latuharhary sebagaimana tersebut di atas, telah membuktikan dengan sendirinya juga betapa RMS didukung penuh oleh “mayoritas” Rakyat Maluku Selatan. Perihal ini adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Dieter Bartels (2017: 685, 687 & 689): “Namun hal itu tidak mematahkan perlawanan orang ‘Ambon’ (Maluku – Penulis), bahkan justeru meningkatkan dukungan kepada RMS serta menciptakan rasa solidaritas yang tinggi dimana situasi seperti itu mungkin tidak pernah muncul lagi sejak zaman pemberontakan Pattimura, memperkuat semangat bertempur demi keselamatan etnik. … Pada suatu saat, karena merasa sakit hati sebab kekalahan yang begitu besar, dengan amarah yang meluap-luap Slamet Riyadi berteriak akan membinasakan semua orang ‘Ambon’ (Maluku – Penulis) … Menurut perkiraan kaum Republik (Indonesia – Penulis), sekitar 2/3 (66,67% – Penulis) penduduk mendukung aksi-aksi RMS sehingga ratusan warga sipil, banyak diantaranya pemuda, dipenjarakan”.
Para pemuda yang dipenjarakan sebagaimana tersebut di atas adalah bagian dari apa yang dinamakan: “Sukarelawan”. Dieter Bartels (2017: 686) menyebut para sukarelawan ini, sebagai: “Luar biasa berani walau tanpa pengalaman militer”. Salah satu contoh keberanian yang luar biasa dari para sukarelawan ini adalah sebagaimana yang ditulis oleh Ben van Kaam dalam halaman 127 dari buku dibawah judul, The South Moluccans: Background to the Hijackings, yang diterbitkan di London, Inggris, pada tahun 1980 oleh C. Hurst & Co.: “Sekelompok sukarelawan terdiri atas 12 (dua belas) anak sekolah yang masih remaja merebut kembali Benteng Victoria beserta barak-barak militernya. … Di sana mereka menawan seluruh garnisun yang terdiri atas 80 (delapan puluh) prajurit”. Dalam pertempuran di Benteng Victoria ini juga, Komandan Group II GOM III, Letnan Kolonel (TNI) Ignatius Slamet Riyadi (1927-1950) tewas tertembak tidak jauh dari gerbang depan Benteng Victoria (Bartels, 2017: 686). Semangat perlawanan para “sukarelawan” sebagaimana tersebut di atas, setidak-tidaknya dipengaruhi juga oleh pidato Sersan Mayor (KNIL) Tahapary (Bartels, 2017: 683): “ … Seandainya ada orang yang hendak merampas bendera kami, maka lakukanlah, kami menunggumu. Kami siap untuk mengorbankan diri demi mempertahankan tanah air kami sampai titik darah yang penghabisan … “.
Perlawanan heroik AP-RMS dan Rakyat Maluku Selatan yang tergabung dalam pasukan “Sukarelawan” terhadap APRIS (TNI) adalah sebagaimana yang dikisahkan oleh Jenderal TNI Angkatan Darat (AD) Leonardus Benyamin Moerdani (1932-2004) seperti yang ditulis oleh Julius Pour dalam halaman 107 dari buku dibawah judul, Benny Moerdani Profil Prajurit Negarawan, yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 1993 oleh penerbit Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman, bahwa: “AP-RMS bertahan mati-matian ketika menghadapi serbuan APRIS. Perlawanan keras dari pihak RMS ini dapat terlihat, karena meskipun pendaratan pasukan APRIS di Pulau Buru sudah berlangsung pada pertengahan bulan Juli tahun 1950, namun serangan langsung ke Kota Ambon baru bisa dilanjutkan pada sekitar bulan November tahun 1950. Selama lebih dari 4 (empat) bulan, pasukan APRIS harus terpaku tanpa mampu memperluas lagi wilayah yang dapat dibebaskannya. Kemajuan operasi pasukan APRIS hanya dapat diperoleh setelah diawali dengan kombinasi serangan gencar dari darat, laut, dan udara. Kedudukan AP-RMS akhirnya baru dapat diserbu. Pertempuran sengit untuk menjebol pertahanan Kota Ambon, ibukota Negara RMS, berlangsung selama 6 (enam) hari 6 (enam) malam”.
Dalam hubungan dengan terjadinya peristiwa seperti yang dikisahkan oleh Jend. TNI-AD L. B. Moerdani sebagaimana tersebut di atas, Dieter Bartels (2017: 868) & J. A. Puar (1956: 100) juga menulis, bahwa: “ … tanpa diduga TNI mendaratkan pasukan di Kota Ambon pada hari Jum’at, tanggal 3 November 1950 dan terjadilah pertempuran dari rumah ke rumah selama satu minggu yang mengakibatkan Kota Ambon hanya tinggal puing-puing belaka”. … “Pada hari Jum’at tanggal 3 November 1950 itu juga, Kota Ambon telah direbut mati-matian dengan pertempuran seorang lawan seorang … meskipun kota Ambon terbakar selama 6 (enam) hari, tetapi pemerintah RMS dan AP-RMS masih dapat bertahan selama 14 (empat belas) hari. Pada hari Rabu, tanggal 29 November 1950, pemerintah RMS dan AP-RMS memilih mundur ke Pulau Seram dengan melintasi Selat Haruku dan Selat Saparua”. Pertempuran lain di Pulau Ambon yang tidak kalah sengitnya dengan pertempuran di Kota Ambon adalah pertempuran di Waitatiri yang oleh Kolonel Infantri TNI-AD Herman Pieters (1924-1996) – Panglima Daerah Militer XV/Pattimura yang pertama – dianalogikan sebagai berikut: “Jika Negeri Belanda mempunyai pertempuran Arnheim, Afrika mempunyai El-Alamien, maka Ambon mempunyai Waitatiri” (Puar, 1956: 96).
Jika merujuk pada keseluruhan uraian penjelasan ilmiah dan/atau akademik maupun kenyataan dan/atau fakta atas peristiwa dan/atau kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa: “telah terjadi suatu perbuatan ‘penyerbuan dan/atau invasi’ (invasion) dan ‘serangan dan/atau agresi’ (aggression) yang disusul kemudian dengan tindakan ‘pendudukan dan/atau okupasi’ (occupation) dan lalu tindakan ‘pencaplokan dan/atau aneksasi’ (annexation) oleh NKRI terhadap Negara RMS”. Jika mengacu pada ketentuan hukum internasional, maka dapat disimpulkan pula, bahwa: “perbuatan invasi dan agresi yang dilanjutkan dengan tindakan okupasi serta aneksasi NKRI terhadap Negara RMS adalah sama dengan perbuatan invasi dan agresi yang dilanjutkan dengan tindakan okupasi serta aneksasi Negara Israel terhadap Palestina”.
Jika perbuatan invasi dan agresi yang dilanjutkan dengan tindakan okupasi serta aneksasi NKRI terhadap Negara RMS adalah “sama dengan” perbuatan invasi dan agresi yang dilanjutkan dengan tindakan okupasi serta aneksasi Negara Israel terhadap Palestina, maka pidato Retno Marsudi di depan “mata” seluruh dunia pada hari Jum’at, tanggal 23 Pebruari 2024, jam: 12.10 pm – 12.40 pm, melalui Mahkamah Internasional yang menentang pendudukan Israel atas wilayah Palestina, adalah: “SUATU IRONI”. Karena akan muncul pertanyaan sebaliknya, bagaimana dengan pencaplokan NKRI atas Negara RMS (???).

Pidato “Standard Ganda” Retno Marsudi
Retno Marsudi memulai pidatonya dengan memberitahukan kepada ketua dan para anggota hakim Mahkamah Internasional serta semua hadirin, bahwa: “Saya meninggalkan pertemuan G20 saya di Rio de Janeiro untuk berdiri di hadapan anda pada hari ini atas nama Pemerintah Republik Indonesia untuk menyatakan solidaritas Rakyat Indonesia mengenai suatu masalah yang sangat penting dan serius suatu masalah yang menyentuh kemanusiaan kita yang rapuh”. Pernyataan Retno Marsudi ini merupakan suatu bukti kuat bahwa pemerintah NKRI menganggap perbuatan invasi dan agresi yang dilanjutkan dengan tindakan okupasi serta aneksasi Negara Israel terhadap Palestina adalah perihal penting bahkan lebih penting dari pertemuan G20 itu sendiri yang sebenarnya juga: “tidak kurang penting”.

Peristiwa perbuatan invasi dan agresi yang dilanjutkan dengan tindakan okupasi serta aneksasi Negara Israel terhadap Palestina sebagaimana tersebut di atas, dan peristiwa perbuatan invasi dan agresi yang dilanjutkan dengan tindakan okupasi serta aneksasi NKRI terhadap Negara RMS adalah 2 (dua) kasus yang berbeda dari sisi ‘waktu’ (tempus) kejadian dan dari segi ‘tempat’ (locus) peristiwa, tetapi memiliki pokok persoalan dan/atau pokok masalah yang sama, yaitu: “Invasi (Invasion), Agresi (Aggression), Okupasi (Occupation), dan Aneksasi (Annexation)”. Invasi dan agresi biasanya mendahului okupasi dan aneksasi, meskipun tidak selamanya okupasi dan aneksasi didahului oleh invasi dan agresi. Invasi dan agresi maupun “okupasi-ilegal” dan aneksasi adalah perbuatan dan/atau tindakan dengan menggunakan kekerasan dan/atau kekuatan ‘bersenjata’ (militer) melalui jalan: “Perang”.
Invasi merupakan suatu istilah umum dari tindakan ‘strategis’ (bukan taktis) militer dalam skala besar guna kepentingan jangka panjang, dimana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain, dengan tujuan untuk menguasai daerah tersebut dan/atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. Invasi bisa menjadi penyebab perang atau langkah untuk menyelesaikan perang oleh pihak tertentu atau dapat menjadi inti dari perang itu sendiri. Sementara itu, Wagiman, S.Fil., SH., MH., dan Anasthasya Saartje Mandagi, SH., MH., Dalam halaman 10 dari buku dibawah judul, Terminologi Hukum internasional, yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 2016 oleh penerbit Sinar Grafika, memberikan pengertian secara umum pada istilah agresi, sebagai: “Penggunaan kekerasan dan senjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan integritas wilayah dan kemerdekaan politik dari negara lain atau dengan cara yang tidak konsisten dengan Piagam PBB”.
Sekalipun Hukum Internasional umum yang berlaku secara universal belum menghasilkan suatu defenisi yang pasti mengenai agresi, tetapi agresi telah menjadi salah satu jenis ‘kejahatan internasional’ (International Crime) dengan tingkat keseriusan ‘sangat berbahaya’ (significant), bahkan agresi telah juga menjadi salah satu dari 4 (empat) jurisdiksi ‘Mahkamah Pidana Internasional’ (international Criminal Court (ICC)) sebagaimana tersebut dalam Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional yang dihasilkan di Roma, pada hari Jum’at, tanggal 17 Juli 1998, Bagian 2 tentang Jurisdiksi, Penerimaan dan Hukum yang berlaku, Pasal 5 tentang Kejahatan yang berada dalam Jurisdiksi Mahkamah, ayat (1): “Jurisdiksi Mahkamah ini terbatas pada kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai Jurisdiksi sesuai dengan statuta ini sehubungan dengan kejahatan-kejahatan berikut: (a) Kejahatan Genosida; (b) Kejahatan Terhadap Kemanusiaan; (c) Kejahatan Perang; (d) Kejahatan Agresi” (Barriga, Stefan (2015) Kejahatan Agresi. Di dalam: Mangai Natarajan, Kejahatan dan Pengadilan Internasional. Jakarta: Nusamedia, h. 336).
Jika merujuk pada status RMS sebagai suatu negara yang berdaulat dan merdeka berdasarkan hukum internasional, maka invasi militer NKRI terhadap Negara RMS pada tahun 1950 dapat dikategorikan sebagai “agresi (aggression)” sebab ‘invasi militer NKRI’ (melalui GOM III) terhadap Negara RMS, adalah: “penggunaan kekuatan dan/atau kekerasan ‘bersenjata’ (militer) melalui jalan perang oleh NKRI terhadap kedaulatan integritas wilayah dan kemerdekaan politik dari Negara RMS yang secara nyata, terang dan jelas telah merupakan suatu cara yang tidak konsisten dengan Piagam PBB, khususnya Bab I tentang Tujuan-tujuan dan Prinsip-prinsip, Pasal 2 tentang Prinsip-prinsip, ayat (4): “Segenap Anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun juga yang bertentangan dengan Tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Dengan demikian, dapat disebutkan dalam kata lain, bahwa: “NKRI telah melakukan salah satu jenis ‘kejahatan internasional’ (International Crime) dengan tingkat keseriusan ‘sangat berbahaya’ (significant), dimana ‘kejahatan agresi’ (crime of aggression) telah menjadi salah satu dari 4 (empat) Jurisdiksi ICC”.
Jika dihubungkan dengan pengertian agresi dalam terminologi hukum internasional sebagaimana tersebut di atas, maka Israel tidak dapat dikategorikan sebagai telah melakukan “agresi” terhadap Palestina, sebab ketika Israel diproklamasikan sebagai suatu Negara yang berdaulat dan merdeka pada hari Jum’at, tanggal 14 Mei 1948, status Palestina bukanlah sebagai suatu Negara yang berdaulat dan merdeka, bahkan status Palestina sebagai suatu Organisasi Pembebasan dengan nama ‘Organisasi Pembebasan Palestina’ (Palestinian Liberation Organization (PLO)) baru terbentuk di Aljir, Aljazair, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 1964, dengan tujuan untuk: “Kemerdekaan Palestina”. Sehingga dengan kata lain dapat disebutkan, bahwa: “oleh karena pada saat itu – hari Jum’at, tanggal 14 Mei 1948 – status Palestina adalah bukan sebagai suatu Negara yang berdaulat dan merdeka, maka Israel tidak dapat disebut sebagai telah melakukan agresi terhadap Palestina”.
Status Palestina dalam Negara Israel oleh Hukum Internasional kemudian diakomodir melalui Konvensi Jenewa ke IV, hari Jum’at, tanggal 12 Agustus 1949 (lihat: UNDoc. A/32/144 Annex I) tentang Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang, khususnya Protokol Tambahan – I tahun 1977 mengenai Perlindungan terhadap Korban-korban Pertikaian-pertikaian Bersenjata Internasional, Bagian I tentang Ketentuan-ketentuan Umum, Pasal 1 tentang Azas-azas Umum dan Ruang Lingkup Penerapan, ayat (4), sebagai: “Pendudukan Asing (Alien Occupation)”. Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa: “Israel tidak pernah melakukan perbuatan ‘kejahatan agresi’ (crime of aggression) yang telah menjadi salah satu dari 4 (empat) Jurisdiksi ICC, bahkan salah satu jenis ‘kejahatan internasional’ (International Crime) dengan tingkat keseriusan ‘sangat berbahaya’ (significant)”. Dalam konteks ini, dapat disebutkan dengan kata lain, bahwa: “perlakuan NKRI terhadap Negara RMS adalah ‘lebih jahat’ (Kejam) daripada perlakuan Israel terhadap Palestina”.
Pendudukan dan/atau okupasi (occupation) dalam hukum internasional merupakan salah satu dari beberapa cara untuk memperoleh ‘kedaulatan’ (sovereignty) atas ‘wilayah dan/atau teritori’ (territory). Secara singkat, okupasi adalah: “cara perolehan kedaulatan teritorial melalui pendudukan secara damai atas suatu ‘terrae nullius’ (wilayah tidak bertuan (no mans land))” (Starke, J. G. (2008) Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, Jilid 1, Ed. X, Cet. 9, h. 214). Tentang okupasi ini, Prof. Lassa Francis Lawrence Oppenheim, MA., LL.D., & Prof. Sir. Hersch Lauterpacht, QC., LL.D., FBA., mengemukakan dalam halaman 555 dari buku dibawah judul, International Law a Treaties, vol. I – Peace, eighth edition, yang diterbitkan di London, Inggris, pada tahun 1955 oleh penerbit Longmans, bahwa: “Satu-satunya wilayah yang dapat dijadikan objek pendudukan adalah wilayah yang belum menjadi milik negara lain, baik yang tidak berpenghuni, maupun yang dihuni oleh orang-orang yang masyarakatnya tidak dianggap sebagai suatu negara; … (the only territory which can be the object of occupation is that which does not already belong to another state. Whether it is uninhabited or inhabited by person whose community is not considered to be a state; … )“.
Dengan demikian dapat disebutkan dalam kata lain, bahwa: “jika suatu okupasi tidak dilakukan secara damai tetapi dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan/atau kekuataan ‘bersenjata’ (militer) melalui jalan perang, maka okupasi tersebut adalah okupasi yang ‘tidak sesuai aturan hukum’ (illegal)”. Dalam hubungan dengan kasus Israel-Palestina, ketika Israel diproklamasikan sebagai suatu Negara yang berdaulat dan merdeka pada hari Jum’at, tanggal 14 Mei 1948, wilayah Negara Israel adalah wilayah yang dimandatkan oleh “Liga Bangsa-Bangsa (LBB) (League of Nations)” kepada Negara Kerajaan Inggris pada hari Minggu, tanggal 25 April 1920. Inggris baru mengembalikan “mandat” atas wilayah tersebut kepada PBB pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 1948, sehari setelah Israel memproklamasikan dirinya sebagai suatu Negara yang berdaulat dan merdeka, yaitu pada hari Jum’at, tanggal 14 Mei 1948.
Wilayah “mandat” sebagaimana tersebut di atas adalah suatu wilayah yang secara mayoritas dihuni oleh penduduk “Arab” dan penduduk “Yahudi”. Secara faktual dan dalam kenyataannya, wilayah ini adalah wilayah “sengketa” antara penduduk Arab dan penduduk Yahudi. Dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Inggris sebagai pemegang mandat melalui Komisi Peel (Peel Commission) pada tahun 1937 dan melalui Komisi Woodhead (Woodhead Commission) pada tahun 1938 telah mengusulkan “pembagian wilayah” atas wilayah Arab dan wilayah Yahudi, tetapi ditolak oleh penduduk Arab. Pada hari Sabtu, tanggal 29 November 1947, MU-PBB menerbitkan Resolusi, nomor: 181, tentang pembagian wilayah mandat Inggris dalam bentuk pembentukkan Negara Arab dan Negara Yahudi yang berdaulat dan merdeka. Akan tetapi, sehari setelah diterbitkannya resolusi ini, terjadi peristiwa peperangan antara penduduk Arab dengan penduduk Yahudi. Setahun kemudian, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 1948, ketika Inggris menyerahkan wilayah mandatnya itu kepada PBB atau sehari setelah penduduk Yahudi memproklamasikan berdirinya Israel sebagai suatu negara yang berdaulat dan merdeka yaitu, hari Jum’at, tanggal 14 Mei 1948, terjadilah peristiwa: “Perang Arab-Israel pertama”.
Perang Arab-Israel yang pertama ini, adalah peristiwa perang “antar negara” yang pertamakali terjadi dalam wilayah bekas mandat Inggris. Perang tersebut dimulai ketika pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 1948, pasukan tentara dari Negara-negara, Mesir, Transyordania, Suriah, dan Irak melakukan serangan militer terhadap Negara Israel. Perang yang berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan itu berakhir dengan dikuasainya secara “mayoritas” wilayah bekas mandat Inggris oleh Israel, sementara “sisanya” yaitu, Jerusalem Timur dan Tepi Barat dikuasai oleh Transyordania, sedangkan Jalur Gaza dikuasai oleh Mesir. Peristiwa peperangan antara Israel dan Penduduk Arab di wilayah bekas mandat Inggris baru mulai terjadi ketika PLO didirikan di Aljazair pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 1964. Pada mulanya, PLO bertujuan untuk mendirikan Negara Arab di seluruh wilayah bekas Mandat Inggris, dan menghapus Negara Israel dari peta dunia. akan tetapi, PLO kemudian mengakui kedaulatan Israel sebagai suatu Negara dalam Perjanjian Oslo pertama yang ditandatangani di Washington DC., Amerika Serikat, pada hari Senin, tanggal 13 September 1993. Pada saat ini, PLO hanya bertujuan untuk memperoleh status Negara Arab di wilayah Tepi Barat dan di wilayah Jalur Gaza yang diduduki oleh militer Israel sejak “Perang Arab-Israel ketiga” pada tahun 1967, yang menjadi terkenal dengan sebutan: “Perang 6 hari”.
Dalam konteks sebagaimana tersebut di atas, oleh karena status PLO yang adalah “bukan negara”, maka pendudukan Israel dengan penggunaan kekerasan dan/atau kekuatan ‘bersenjata’ (militer) melalui jalan perang atas wilayah Tepi Barat dan wilayah Jalur Gaza telah menempatkan Isreal sebagai suatu negara yang telah melakukan: “Pendudukan Ilegal (Illegal Occupation)”. Konvensi Jenewa ke IV tanggal 12 Agustus 1949 (lihat: UNDoc. A/32/144 Annex I) khususnya Protokol Tambahan – I tahun 1977, Bagian I, Pasal 1, ayat (4), menyebutnya, sebagai: “Pendudukan Asing (Alien Occupation)”. Namun demikian, status Israel sebagai “pendudukan ilegal (ilegal occupation) dan/atau pendudukan asing (alien occupation)” secara perlahan-lahan tetapi pasti mulai bergeser ke arah status “aneksasi”, ketika PLO yang mendasarkan dirinya pada Resolusi MU-PBB, nomor: 181 tahun 1947, memproklamasikan “Jalur Gaza dan Tepi Barat” sebagai suatu Negara yang merdeka dan berdaulat dengan nama “Palestina” di Aljir, Aljazair, pada hari Selasa, tanggal 15 November 1988. nama “Palestina” ini, kemudian diakui oleh MU-PBB sebagai pengganti nama PLO.
Dengan lahirnya Palestina sebagai suatu Negara yang berdaulat dan merdeka sebagaimana tersebut di atas, maka posisi kasus “Israel-PLO” kemudian berubah pula menjadi kasus “Israel-Palestina”. Karena pada saat ini, status PLO juga sudah berubah dari suatu ‘Gerakan Pembebasan Nasional’ (National Liberation Movement) yang melakukan ‘Perang Pembebasan Nasional’ (War of National Liberation) menjadi Negara Palestina (Lihat: ketentuan Konvensi Jenewa ke IV, hari Jum’at, tanggal 12 Agustus 1949, khususnya Protokol Tambahan – I tahun 1977, Bagian I, Pasal 1, ayat (4)), maka status Israel sebagai “pendudukan ilegal/pendudukan asing” juga mulai berubah ke arah status: “Aneksasi (Annexation)”. Perihal ini, adalah sebagaimana yang telah disinggung oleh Retno Marsudi dalam menit ke 12 dan detik ke 45 dari pidatonya di Mahkamah Internasional, bahwa: “Kedua, aneksasi ilegal dari OPT. Sebagai kekuatan pendudukan, Israel secara hukum berkewajiban untuk menjaga pendudukannya sementara. Hal ini dilanggar oleh Israel karena mereka mencoba membuat pendudukan ini permanen dan juga untuk menganeksasi bagian dari wilayah yang diduduki. Secara hukum, seharusnya tidak ada keadaan dimana Israel diizinkan menganeksasi bagian dari wilayah yang diduduki”.
Sama seperti ‘pendudukan dan/atau okupasi’ (occupation) yang dalam hukum internasional merupakan salah satu dari beberapa cara untuk memperoleh kedaulatan atas ‘wilayah dan/atau teritori’ (territory), maka demikian pula dengan: “Aneksasi (Annexation)”. Prof. Dr. Huala Adolf, SH., LL.M., dalam halaman 120 dari buku dibawah judul, Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional, yang diterbitkan di Bandung pada tahun 2022 oleh penerbit Keni Media, memadankan istilah Aneksasi dengan istilah: “Penaklukan (Conquest)”. Sementara L. F. L. Oppenheim, MA., LL.D., & H. Lauterpacht, QC., (1955: 566) menyebut aneksasi atau penaklukan dengan istilah: “Subjugation”. Secara singkat, Dr. Sefriani, SH., M.Hum., (2016: 177) mendefenisikan aneksasi/penaklukan/subjugasi, sebagai: “Penggabungan suatu wilayah negara lain dengan kekerasan atau paksaan ke dalam wilayah negara yang menganeksasi”. Dalam hubungan dengan defenisi tersebut, dapat disimpulkan, bahwa: “jika mengacu pada status Palestina pada saat ini, yaitu sebagai suatu negara yang berdaulat dan merdeka, maka posisi status Israel dalam kasus Israel-Palestina pada saat ini pula dan nanti di masa depan akan semakin mendapat pembenarannya tidak lagi sebagai ‘pendudukan ilegal’ (ilegal occupation) dan/atau ‘pendudukan asing’ (alien occupation) tetapi sudah sebagai: “Aneksasi (Annexation)””.

Dengan mengingat status Palestina sebagai suatu Negara yang berdaulat dan merdeka berdasarkan ketentuan hukum internasional, dan juga status RMS sebagai suatu Negara yang berdaulat dan merdeka berdasarkan ketentuan hukum internasional, maka dapat disebutkan dalam kata lain, bahwa: “peristiwa yang terjadi atas Negara Palestina sebagaimana tersebut di atas, adalah sama persis dengan peristiwa yang juga terjadi atas Negara RMS yaitu, baik Negara Palestina maupun Negara RMS, adalah sama-sama mengalami aneksasi/penaklukan/subjugasi, dimana jika Negara Palestina dianeksasi oleh Negara Israel maka Negara RMS dianeksasi oleh NKRI”. Bedanya, adalah: “jika Negara Israel yang menganeksasi Negara Palestina dengan alasan ‘pembelaan diri’ (suatu prinsip untuk melakukan perang secara sah yang diakui oleh PBB) saja sudah dianggap sebagai telah melanggar ketentuan hukum internasional (Wallace, 1986: 101; Adolf, 2022: 122), maka bagaimana pula dengan Negara RMS yang juga dianeksasi oleh NKRI tetapi tanpa adanya alasan apapun juga (?)”.
Dalam konteks ini, dapat disebutkan dengan kata lain, sekali lagi, bahwa: “perlakuan NKRI terhadap Negara RMS adalah ‘lebih jahat’ (Kejam) daripada perlakuan Israel terhadap Palestina”. Lebih kejam lagi, NKRI tetap menyangkal telah melakukan agresi dan aneksasi terhadap Negara RMS sampai dengan saat ini. Bahkan jauh lebih kejam lagi, NKRI malah balik menuduh Rakyat Maluku Selatan sebagai para “separatis” yang bertindak untuk memisahkan diri dari NKRI melalui proklamasi RMS sebagai suatu Negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan tidak bermaksud untuk mendukung pernyataan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, sebagaimana tersebut dibawah ini, tetapi pernyataan Netanyahu yang mengakui “secara jantan” tindakan Israel dalam menganeksasi Palestina, sekalipun dengan tidak mengucapkan kata “aneksasi” secara terang-terangan, adalah jauh lebih bermartabat daripada NKRI yang secara jelas, terang, dan nyata, telah menganeksasi Negara RMS, tetapi tidak pernah memiliki ‘niat baik’ (goodwill) untuk mengakuinya sampai dengan saat ini. Pernyataan Netanyahu itu, adalah sebagaimana yang dikutip oleh Retno Marsudi dalam pidatonya: “Saya bangga telah mencegah pendirian negara palestina” … “tidak ada yang akan menghentikan kami … bukan the Haque … dan bukan siapa pun yang lain”.
Cara-cara untuk memperoleh kedaulatan atas ‘wilayah dan/atau teritori’ (territory) dengan penggunaan kekerasan dan/atau kekuatan ‘bersenjata’ (militer) melalui jalan perang seperti, pencaplokan/penaklukan/aneksasi/subjugasi, masih diakomodir oleh hukum internasional sampai dengan tahun 1928, yaitu tahun ketika ditandatanganinya Paris Pact dan/atau Briand-Kellogg Pact dan/atau General treaty for the Renunciation of War pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 1928, oleh Negara-negara: Jerman, Perancis dan Amerika Serikat serta 31 (tiga puluh satu) negara lainnya. Akan tetapi, setelah tahun 1928, cara-cara untuk memperoleh kedaulatan atas ‘wilayah dan/atau teritori’ (territory) dengan penggunaan kekerasan dan/atau kekuatan ‘bersenjata’ (militer) melalui jalan perang seperti, pencaplokan/penaklukan/aneksasi/subjugasi, telah dilarang oleh hukum internasional. Larangan ini, juga terdapat dalam: “Piagam LBB, hari Sabtu, tanggal 10 Januari 1920; Pasal 2, ayat (4), Bab I, Piagam PBB, hari Selasa, tanggal 26 Juni 1945; Putusan Pengadilan Perang Nurnburg, hari Selasa, tanggal 1 oktober 1946; Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB tentang Timur Tengah (UN Security Council Resolution on the Midle East), nomor: 242 (XXII), hari Rabu, tanggal 22 November 1967; dan Statuta Roma, hari Senin, tanggal 1 Juli 2002”.
Disamping itu, Hukum Internasional juga telah melarang semua Negara untuk tidak mengakui perolehan kedaulatan atas ‘wilayah dan/atau teritori’ (territory) oleh suatu Negara terhadap Negara lain yang dilakukan dengan penggunaan kekerasan dan/atau kekuatan ‘bersenjata’ (militer) melalui jalan perang seperti, pencaplokan/penaklukan/aneksasi/subjugasi. Dimana, jika ada suatu negara yang mengakui perolehan kedaulatan atas ‘wilayah dan/atau teritori’ (territory) oleh suatu negara terhadap negara lain yang dilakukan dengan penggunaan kekerasan dan/atau kekuatan ‘bersenjata’ (militer) melalui jalan perang seperti, pencaplokan/penaklukan/aneksasi/subjugasi, maka pengakuan itu adalah tidak sah karena telah melanggar ketentuan hukum internasional. ketentuan ini, adalah sebagaimana yang terdapat dalam: “The Stimson Doctrine of Non-Recognition, hari Kamis, tanggal 7 Januari 1932; Pasal 17, Piagam Bogota dan/atau piagam ONA/OAS, hari Jum’at, tanggal 30 April 1948; Pasal 11, Rancangan Deklarasi tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Dasar Negara-negara, hari Selasa, tanggal 6 Desember 1949; dan Paragraf 10, Deklarasi tentang prinsip-prinsip hukum internasional mengenai Hubungan-hubungan Bersahabat dan kerjasama antara Negara-negara sesuai dengan Piagam PBB, hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 1970”.
Jika merujuk pada aturan-aturan hukum internasional sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa: “Aneksasi NKRI atas Negara RMS maupun aneksasi Negara Israel atas Negara Palestina adalah telah melanggar hukum internasional, sebab baik Negara RMS maupun Negara Palestina merupakan Negara-negara yang berdaulat dan merdeka, yang lahir setelah berlakunya ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai larangan terhadap perbuatan aneksasi suatu negara terhadap negara lainnya, dimana RMS lahir sebagai suatu Negara yang berdaulat dan merdeka pada hari Selasa, tanggal 25 April 1950 dan Palestina lahir sebagai suatu Negara yang berdaulat dan merdeka pada hari Selasa, tanggal 15 November 1988, beberapa tahun setelah ditandatanganinya ‘Pakta Paris’ (Paris Pact) pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 1928, dan aturan-aturan hukum internasional lainnya mengenai perihal aneksasi yang muncul dikemudian hari”. Dalam hubungan dengan perihal ini, dapat disimpulkan pula, bahwa: “jika ada negara-negara di dunia yang mengakui aneksasi NKRI atas Negara RMS maupun ada negara-negara di dunia yang mengakui aneksasi Negara Israel atas Negara Palestina, maka pengakuan tersebut adalah tidak sah karena telah melanggar ketentuan hukum internasional sebagaimana tersebut di atas”.

Pencaplokan/penaklukan/aneksasi/subjugasi dilarang oleh hukum internasional sebab dalam hukum Internasional ada berlaku prinsip, bahwa: “Kekuatan tidak dapat memberi ‘alas hak yang baik’ (good title) (Wallace, 1986: 101)”. Prinsip ini telah di-interpretasikan bahwa wilayah tidak dapat dituntut secara sah melalui penggunaan kekerasan dan/atau kekuatan ‘bersenjata’ (militer) melalui jalan perang, bahkan jika penggunaan kekerasan dan/atau kekuatan ‘bersenjata’ (militer) melalui jalan perang itu sesuai dengan Piagam PBB – yaitu: “pertahanan diri”. Berdasarkan prinsip ini pula, maka Dewan Keamanan (DK) PBB menerbitkan Resolusi tentang Timur Tengah, nomor: 242 (XXII), hari Rabu, tanggal 22 November 1967, yang menyerukan penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah pendudukan di Tepi Barat dan wilayah pendudukan di Jalur Gaza serta menegaskan ketidak-absahan pemilikan wilayah melalui peperangan (Wallace, 1986: 101; Adolf, 2022: 122). Perihal ini, adalah sebagaimana yang diucapkan juga oleh Retno Marsudi dalam pidatonya di Mahkamah Internasional: “Dewan keamanan PBB dalam berbagai resolusinya telah mengukuhkan prinsip yang mapan bahwa perolehan wilayah dengan perang adalah tidak dapat diterima. Ini adalah prinsip mutlak yang berlaku bahkan dalam keadaan dimana perang dilakukan secara sah. Seperti dalam bela diri yang jelas bukan kasus untuk Israel”.
Retno Marsudi kemudian mengulangi lagi seruan penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah pendudukan sebagaimana yang telah diserukan oleh Dewan Keamanan (DK) PBB melalui Resolusi tentang Timur Tengah (United Nations Security Council Resolution on the Midle East), nomor: 242 (XXII), hari Rabu, tanggal 22 November 1967: “Oleh karena itu, sangat penting agar Israel menarik mundur pasukannya. Dengan sifat ilegal dari pendudukan ini, penarikan pasukan Israel tidak boleh dilakukan dengan prasyarat atau tunduk pada negosiasi apapun. Mereka harus menarik diri sekarang. Saya ulangi, mereka harus menarik diri sekarang. Israel juga harus diwajibkan untuk memberikan ganti rugi balik kepada Negara Palestina maupun kepada Rakyat Palestina”. Dalam konteks ini – dengan mengabaikan pemberian ganti rugi balik kepada Negara RMS maupun kepada Rakyat Maluku Selatan – pertanyaan prinsipnya adalah, bagaimana dengan pasukan-pasukan NKRI yang masih bercokol dan terus bertambah banyak jumlahnya di Maluku pada saat ini (???). Seharusnya adalah sebagaimana apa yang menjadi kesimpulan Karen Parker (1996: 17): “Negara RMS diduduki secara tidak sah oleh NKRI yang segera harus menarik mundur semua orang NKRI dan seluruh pasukan tentaranya dari wilayah Negara RMS”.
Dengan dilarangnya aneksasi oleh hukum internasional sejak diterimanya Piagam LBB, hari Sabtu, tanggal 10 Januari 1920 (Brownlie, Ian (1990) Principles of Public Internastional Law. Oxford: Clarendon Press, p. 131), dan Piagam PBB, hari Selasa, tanggal 26 Juni 1945, maka semua peristiwa aneksasi yang terjadi di seluruh dunia – sejak tahun 1920 hingga saat ini dan nanti dimasa depan – yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lainnya harus diakhiri dengan sesegera mungkin. Pengakhiran aneksasi ini, dengan meminjam kata-kata Retno Marsudi sendiri: “tidak boleh dilakukan dengan prasyarat atau tunduk pada negosiasi apapun”. Artinya, Aneksasi yang dilakukan oleh NKRI atas Negara RMS dan aneksasi yang dilakukan oleh Negara Israel atas Negara Palestina harus segera diakhiri, dan pengakhiran Aneksasi oleh NKRI atas Negara RMS serta pengakhiran aneksasi oleh Negara Israel atas Negara Palestina, sekali lagi, dengan meminjam kalimat Retno Marsudi sendiri: “tidak boleh dilakukan dengan prasyarat atau tunduk pada negosiasi apapun”. Bahkan sekalipun NKRI dan Negara Israel tidak kunjung mengakhiri aneksasi mereka terhadap Negara RMS dan Negara Palestina, Negara Palestina dan Negara RMS: “Akan tetap ada’ (will still exist), akan tetap hidup (will stay alive), dan ‘tidak akan pernah mati’ (will never die)”.
Perihal sebagaimana tersebut di atas, adalah seperti yang dikemukakan oleh Prof. Eric de Brabandere dalam Expert Opinion dibawah judul, Kelangsungan Keberadaan Republik Maluku Selatan (RMS) Dibawah Hukum Internasional, dalam kasus Negara RMS melawan NKRI di Pengadilan Belanda pada tahun 2011, dan seperti yang dikemukakan juga oleh Prof. Noelle Higins dalam Expert Opinion dibawah judul, Pendapat Tentang Status RMS, dalam kasus yang sama, bahwa, aneksasi tidak dapat dengan sendirinya secara serta merta dan/atau secara otomatis menjadi ‘alas hak dan/atau titel’ (title) yang sah atas ‘wilayah dan/atau teritory’ (territory) yang diperoleh negara pelaku aneksasi. Wilayah/teritori yang diperoleh negara pelaku aneksasi tetap tunduk pada hak hukum negara korban aneksasi. Sekalipun telah terjadi aneksasi, kedaulatan negara korban aneksasi tetap ada dan tidak hilang, dan kedaulatan negara korban aneksasi itu juga tidak dapat dengan sendirinya secara serta merta dan/atau secara otomatis berpindah dan/atau beralih kepada negara pelaku aneksasi. Perihal ini dapat dikatakan demikian karena aneksasi telah melanggar ketentuan hukum internasional tentang jus cogens dan/atau ‘norma dasar hukum internasional umum’ (peremtory norm of general international law) yang berlaku secara universal.
Eric de Brabandere, dan Noelle Higins, selanjutnya menyatakan bahwa, jika terjadi aneksasi terhadap suatu negara oleh negara lain, maka negara korban aneksasi tidak mati dan/atau tidak lenyap, tetapi tetap ada dan/atau tetap hidup, sekalipun negara korban aneksasi itu dikuasai oleh negara pelaku aneksasi dalam jangka waktu lama. Dalam aturan hukum internasional, tidak ada ketentuan mengenai ‘jangka waktu yang diperlukan’ (tanggal kritis (critical date) (Wallace: 1986: 99)) untuk memutuskan kematian suatu negara yang menjadi korban aneksasi. Praktek negara-negara juga tidak memperlihatkan kepastian tentang perihal ini. Dengan demikian, adalah menjadi jelas dengan sendirinya bahwa, sekalipun telah terjadi aneksasi oleh suatu negara terhadap negara lain, negara yang dianeksasi itu: “Tidak mati (not dead), tetap ada’ (still exist), dan tetap hidup (stay alive)”.
Jika aneksasi merupakan salah satu dari beberapa cara untuk memperoleh kedaulatan atas wilayah yang telah dilarang oleh hukum internasional, maka “hak untuk menentukan nasib sendiri” adalah satu-satunya cara untuk memperoleh kedaulatan atas wilayah yang diakui sepenuh-penuhnya oleh hukum internasional. Pengakuan ini dapat dilihat dari telah ditetapkannya hak untuk menentukan nasib sendiri oleh hukum internasional sebagai jus cogens yang bukan merupakan ‘norma biasa’ (ordinary norm). Disamping itu, Hak untuk menentukan nasib sendiri telah merupakan juga ‘norma tertinggi’ (the highest norm) dalam hukum internasional, dan bukan suatu ‘norma yang bersifat mengatur’ (jus dispositivum) yang ‘dapat disimpangi’ (derogable) dan/atau ‘dapat dicabut’ (alianable), tetapi hak untuk menentukan nasib sendiri adalah suatu ‘norma yang bersifat memaksa’ (imperative norm) yang ‘tidak dapat diabaikan’ (non-derogable) bahkan ‘tidak dapat dicabut’ (inalianable), dimana semua jus dispositivum harus sesuai dengan jus cogens karena jika suatu jus dispositivum tidak sesuai dengan jus cogens, maka jus dispositivum dimaksud akan “batal demi hukum (ex nunc)” atau “batal secara otomatis (null and void)” (Situni, F. A. Whisnu (1989) Identifikasi Dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional, Bandung, Mandar Maju, h. 101).
Terhadap norma jus cogens sebagaimana tersebut di atas, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., menulis dalam halaman 593 dari tulisan dibawah judul, Studi Awal Tentang Perjanjian Internasional Yang Bertentangan, yang diterbitkan pada tahun 1992 (XXII) oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia melalui Majalah dua bulanan, Hukum dan Pembangunan, nomor: 6, bahwa, jika ditelaah dari sudut pandang ilmu perundang-undangan, maka dikenal suatu teori yang menata norma-norma dalam suatu ‘tingkatan’ (hirarki), yaitu teori ‘Stufenbau’ (the higher-lower level approach) dari Hans Kelsen melalui bukunya dibawah judul, Teori Murni Tentang Hukum (The Pure Theory of Law), bahwa: “Every law-applying act is seen as a law-creating act, from the highest norm, the basic norm, to the lowest act of application”, dimana jus cogens berada pada tingkatan ‘norma tertinggi’ (the highest norm), sedangkan piagam PBB berada pada tingkatan ‘norma dasar’ (the basic norm), dan Perjanjian-perjanjian internasional pada umumnya berada pada tingkatan ‘peraturan pelaksanaan’ (the lowest act of application)”. Salah satu peraturan pelaksanaan itu, adalah: “Deklarasi tentang prinsip-prinsip hukum internasional mengenai Hubungan-hubungan Bersahabat dan kerjasama antara Negara-negara sesuai dengan Piagam PBB”.
Dalam hubungan dengan “Hak untuk menentukan nasib sendiri” sebagai salah satu cara guna memperoleh kedaulatan atas ‘wilayah dan/atau teritori’ (territory), Paragraf kelima dari ‘prinsip tentang kesetaraan hak-hak dan penentuan nasib sendiri dari rakyat’ (the principle of equal rights and self-determination of peoples) dalam Resolusi MU-PBB, nomor: 2625 (XXV), hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 1970, mengenai ‘Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan-hubungan Bersahabat dan Kerjasama antara Negara-negara sesuai dengan piagam PBB’ (Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations), menyatakan, bahwa: “Pembentukan Negara yang berdaulat dan merdeka, penggabungan atau integrasi dengan Negara yang merdeka secara bebas, atau dengan status politik yang lain, yang secara bebas ditentukan oleh rakyat, merupakan cara-cara pelaksanaan hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri (The establisment of a sovereign and independent state, the free association or integration with an independent State or the emergence into any other political status freely determined by a people constitute modes of implementing the right of self-determination by that people)”.
Secara eksplisit, Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan-hubungan Bersahabat dan Kerjasama antara Negara-negara sesuai dengan piagam PBB sebagaimana tersebut di atas, tidak menyebutkan mengenai mekanisme implementasi dan/atau cara pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri dari rakyat, tetapi Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan-hubungan Bersahabat dan Kerjasama antara Negara-negara sesuai dengan piagam PBB tersebut secara implisit telah menyatakan bahwa, mekanisme implementasi dan/atau cara pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri dari rakyat ini, adalah: “secara bebas ditentukan oleh rakyat”. Dalam hubungan dengan perihal ini, J. G. Starke (2008: 158) menyatakan, bahwa: “Tampaknya, hak untuk menentukan nasib sendiri berkonotasi kepada kebebasan untuk memilih dari rakyat yang belum merdeka melalui ‘plebisit’ (plebiscite) atau metode-metode lainnya untuk memastikan kehendak rakyat”.
Dalam pidatonya yang berdurasi 21 menit dan 32 detik itu, Retno Marsudi juga lebih banyak berbicara mengenai “hak untuk menentukan nasib sendiri” sebagaimana tersebut di atas. Perihal ini adalah seperti apa yang diucapkan sendiri oleh Retno Marsudi dalam pidatonya di Mahkamah Internasional: “Ini harus dimulai dengan menghormati hak-hak fundamental rakyat palestina terutama hak untuk menentukan nasib sendiri yang secara sistematis diabaikan oleh Israel”. Sebelumnya, Retno Marsudi mengatakan: “Dalam mengatasi masalah hak untuk menentukan nasib sendiri dari rakyat Palestina, penting juga untuk mengingatkan diri kita bahwa pendudukan telah menjadi alat untuk menekan hak fundamental tersebut”. Sebelumnya lagi, Retno Marsudi menekankan: “Izinkan saya untuk mengkonfirmasi posisi indonesia, sejalan dengan pandangan Mahkamah Internasional, bahwa pemenuhan hak tersebut merupakan kewajiban erga omnes. Dengan kata lain, semua negara, saya ulangi, semua negara memiliki kewajiban hukum untuk menghormati hak tersebut dan berkontribusi pada pemenuhannya”.
Jika NKRI telah menekankan di hadapan seluruh dunia pada hari Jum’at, tanggal 23 Pebruari 2024, melalui pidato Retno Marsudi di Mahkamah Internasional, bahwa pemenuhan hak untuk menentukan nasib sendiri adalah kewajiban ‘terhadap semua’ (erga omnes), maka bagaimanakah dengan penghormatan NKRI terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri dari Rakyat Negara RMS sebagai suatu kewajiban hukum (?), dan bagaimana pula dengan kontribusi NKRI pada pemenuhan hak untuk menentukan nasib sendiri dari Rakyat Negara RMS, sekali lagi, sebagai suatu kewajiban hukum (?). Penting juga untuk mengingatkan NKRI apabila NKRI tidak mampu untuk mengingatkan dinya sendiri atau NKRI berpura-pura tidak ingat bahwa, aneksasi NKRI terhadap Negara RMS telah menjadi alat guna menekan hak untuk menentukan nasib sendiri dari Rakyat Negara RMS yang adalah hak ‘amat sangat mendasar’ (fundamental/substansial/esensial) dari Rakyat dalam wilayah Negara RMS. Pada akhirnya, NKRI harus mulai dengan menghormati hak-hak fundamental seluruh Rakyat, tidak hanya hak-hak fundamental Rakyat Negara RMS, tetapi juga hak-hak fundamental Rakyat Acheh dan hak-hak fundamental Rakyat Papua, terutama hak untuk menentukan nasib sendiri dari Rakyat Negara RMS, Rakyat Acheh, dan Rakyat Papua, yang secara sistematis telah diabaikan oleh NKRI.
Pada menit ke 20 dan detik ke 15 sebelum Retno Marsudi mengakhiri pidatonya pada menit ke 21 dan detik ke 32, Retno Marsudi menekankan, bahwa: “Kita mendirikan sistem internasional kita saat ini dengan keyakinan bahwa setiap manusia, saya ulangi, setiap manusia tanpa pengecualian, dilindungi oleh hukum”. Kalimat ini, adalah sebuah “bumerang” yang akan berputar kembali menghantam Retno Marsudi seperti kata orang bijak: “senjata makan tuan”. Peristiwa ini terjadi dalam kasus pidana di Pengadilan Negeri Masohi, nomor: 32/Pid.B/2023/PN.Msh atas/nama Terdakwa ANTONIUS LATUMUTUANY alias ANTON. Akan tetapi, dalam konteks ini, pertanyaan prinsipnya adalah, apakah ANTON adalah juga salah seorang dari setiap manusia sebagaimana yang dimaksudkan oleh Retno Marsudi dalam pidatonya itu (?). Sebab, Jika ANTON adalah salah seorang dari setiap manusia yang dimaksudkan oleh Retno Marsudi dalam pidatonya itu, maka ANTON harus dan pasti akan dilindungi oleh hukum, kecuali jika ANTON adalah bukan salah seorang dari setiap manusia yang dimaksudkan oleh Retno Marsudi dalam pidatonya itu, maka ANTON pasti tidak akan dilindungi oleh hukum (!). lalu, jika ANTON tidak dilindungi oleh hukum, maka pertanyaan yang ‘amat sangat mendasar’ (fundamental/substansial/esensial), adalah: “Siapakah ANTON (?)”.

Jawaban dari pertanyaan “siapakah ANTON (?)” sebagaimana tersebut di atas, terdapat pada keputusan Retno Marsudi dalam kedudukan dan jabatannya sebagai MENLU NKRI yang tidak memberikan ‘penjelasan/tanggapan/respons’ (response) terhadap permohonan persetujuan yang diminta oleh Team Kuasa Hukum ANTON dari Kantor Advokasi Dan Bantuan Hukum Semuel Waileruni & Rekan untuk menghadirkan Mr. Johannes Gerardus Wattilete (Presiden Negara RMS in exile di Negara Belanda) sebagai saksi dan/atau ahli yang meringankan bagi ANTON. Permintaan tersebut, adalah sebagaimana yang tertuang dalam Surat, nomor: 33/KABH-SW/X/2023, hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, perihal: “Mohon persetujuan/rekomendasi kehadiran saksi dan/atau ahli pada perkara pidana nomor: 32/Pid.B/2023/PN.Msh an. Terdakwa ANTONIUS LATUMUTUANY”. Dalam konteks ini, Retno Marsudi telah tidak menggunakan kewenangan yang diberikan oleh, point (c), ayat (3), Pasal 11, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia, nomor: 4, tahun 2020, yaitu: “Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di Kedutaan/Konsulat Jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal Saksi dan/atau Ahli berada di luar negeri”.
Oleh karena sikap “mbalelo” dari seorang Retno Marsudi yang tidak kunjung memberikan penjelasan/tanggapan/respons’ (response) yang jelas dan pasti, tentang apakah ia setuju ataukah ia tidak setuju (?), sehingga dengan lewatnya waktu yang telah disepakati bersama antara Hakim dengan Team Pengacara ANTON untuk menghadirkan saksi dan/atau ahli, maka Hakim Pengadilan Negeri Masohi lalu membatalkan rencana Team Pengacara ANTON untuk menghadirkan Mr. J. G. Wattilete sebagai saksi dan/atau ahli yang meringankan bagi ANTON. Team Pengacara ANTON kemudian mengirimkan keputusan pembatalan itu kepada Mr. J. G. Wattilete, melalui surat, nomor: 34/KABH-SW/X/2023, hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, perihal: “Pemberitahuan Penolakan Mendengarkan Pendapat Ahli Pada Perkara Pidana Nomor: 32/Pid.B/2023/PN.Msh an. Terdakwa ANTONIUS LATUMUTUANY”. Dalam konteks ini, Retno Marsudi telah mempertontonkan sikap dan/atau perilakunya yang “arogan dan tidak bertanggungjawab serta tidak beretika bahkan tidak bermoral” sebagai seorang menteri. Sebab mengenai perihal ini, bukanlah masalah setuju atau tidak setuju, tetapi lebih daripada itu adalah persoalan kemampuan untuk memberikan “alasan yang dapat diterima” apabila ia setuju maupun apabila ia tidak setuju.

Dalam hubungan dengan kepastian hukum bagi ANTON, maka dapat disimpulkan, bahwa: “Retno Marsudi telah tidak memberikan persetujuan secara diam-diam”. Dimana perbuatan Retno Marsudi tersebut, secara terang, nyata, dan jelas telah melanggar hak asasi manusia dari ANTON yang diberikan oleh hukum dan Undang-undang untuk memperoleh kesaksian yang meringankan bagi dirinya sebagai seorang terdakwa. Keseluruhan tindakan/perbuatan/aksi (action) pemerintah NKRI sebagaimana tersebut di atas, secara jelas, terang, dan nyata, telah melanggar Konstitusi NKRI itu sendiri, khususnya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 28F, yang merupakan amandemen kedua dari Undang-Undang Dasar NKRI, yang disahkan pada hari Jum’at, tanggal 18 Agustus 2000. Keseluruhan ‘tindakan/perbuatan/aksi’ (action) pemerintah NKRI sebagaimana tersebut di atas, secara jelas, terang, dan nyata, juga telah melanggar Hukum Internasional umum yang berlaku secara universal khususnya Hukum Internasional tentang ‘Hak Asasi Manusia’ (HAM) (Human Rights), terutama Pasal 19 dari ‘Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (SIPOL)’ (International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)) yang mulai berlaku pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 1976, dan yang telah diratifikasi oleh pemerintah NKRI melalui Undang-Undang, nomor: 12, tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.
Penulis mengakhiri dan menutup tulisan ini dengan menjawab pertanyaan, tentang: “Siapakah ANTON (?)”. ANTON, adalah: “Bukti dari standard ganda pidato Retno Marsudi”.
Penulis merupakan Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Politeknik Negeri Ambon

Keterangan Gambar:
- Foto Kiri- Kanan: Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri (MENLU) Negara ‘Republik Indonesia’ (RI), Sumber: CNN Indonesia & Gedung Mahkamah International di Denhag, Belanda. Sumber Artikel Heylaw Edu
- Foto: Karen Parker, J. D. adalah seorang Direktur pada ‘Proyek Hukum Kemanusiaan’ dan Pengacara Hukum pada ‘Asosiasi Pengacara-pengacara Kemanusiaan
- Foto: Johanis Hermanus Manuhutu, Presiden Pertama Republik Maluku Selatan (RMS). Sumber: Wikipedia.org
- Pawai dan Pengibaran Bendera RMS di Desa Aboru, Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Selasa (25/4/2023). Foto: Istimewa
- Penasehat hukum Semuel Waileruny saat mendampingi terdakwa kasus dugaan makar Anthonius Latumutuani, (Aktivis RMS) di Pengadilan Negeri Masohi, Maluku.
- Peta Wilayah Republik Maluku Selatan (RMS). Foto Istimewa
- Penulis saat berada di salah satu ruang sidang dalam gedung ‘Perserikatan Bangsa-Bangsa’ (PBB) ketika mengikuti 18th Session on the United Nations Permanent Forum on Indigenous issues (UNPFII 18th Session) Conference, New York, USA, 22 april 2019 to 3 May 2019.






